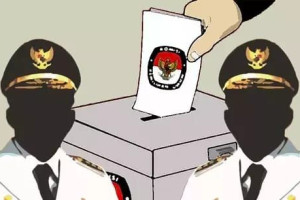Wajah Setelah Tambang
Lubang tambang raksasa mengungkap kerusakan tanah, hilangnya ruang hidup, dan beban yang ditinggalkan industri
- 02 Dec 2025
- Komentar
- 462 Kali

Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
Belum lama ini saya berdiri di tepi sebuah lubang tambang yang ukurannya sulit dicerna. Sebuah cekungan raksasa yang seperti mengiris perut bumi, lebih besar dari apa pun yang pernah saya lihat sebelumnya. Dari tempat saya berdiri, hamparan tanah yang dikeruk membentang sejauh mata mengikuti kontur yang dipaksa turun ke dasar.
Tidak lagi menyerupai lanskap alami, tetapi lebih mirip luka terbuka yang ditinggalkan tanpa perban. Ada kesunyian yang tidak wajar di sekitarnya, seolah tanah itu sendiri tengah menahan napas. Dan saya melihatnya dari jarak yang tidak seharusnya dianggap biasa oleh siapa pun yang hidup di wilayah yang sama.
Yang membuat saya terpaku bukan hanya skala lubangnya, tetapi kenyataan bahwa ini bukan fenomena tunggal. Di Kaltim, lubang-lubang besar itu bertambah dan membesar seperti kata-kata yang tak pernah dibacakan dalam laporan resmi. Mereka hadir diam-diam namun meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja.
Ada wilayah yang seolah dibiarkan berubah menjadi atlas bopen, didefinisikan ulang oleh ekskavator dan izin yang bergerak lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk lokal. Bagi sebagian orang, angka-angka dalam dokumen cukup untuk memahami apa yang terjadi.
Namun bagi saya, satu kali melihat cekungan sebesar itu lebih menjelaskan dari seribu statistik.
Pengalaman berdiri di hadapan lubang raksasa itu mengubah cara saya melihat berita-berita tambang yang selama ini hanya menjadi data dingin di layar ponsel. Hektar yang hilang, konsesi yang dilepas, reklamasi yang entah kapan dimulai.
Angka-angka itu terdengar teratur dan rapi, seperti laporan keuangan perusahaan yang tidak ingin tampak berantakan. Namun begitu saya menyaksikannya langsung, angka-angka itu tampak menyusut, kehilangan makna.
Karena realitasnya jauh lebih besar, jauh lebih dalam, dan jauh lebih menyentuh masa depan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Lubang sebesar itu bukan sekadar ruang kosong. Wujudnya seperti mulut gelap yang menelan potongan-potongan ruang hidup tanpa mengembalikannya.
Masalahnya bukan semata-mata keberadaan industri tambang. Persoalannya adalah bagaimana kita membiarkan bumi dikeruk lebih cepat daripada kita meminta pertanggungjawaban dari mereka yang mengambilnya.
Lubang-lubang itu tidak hanya mengubah fisik tanah, tetapi juga cara orang memandang tempat tinggalnya. Ketika sebuah desa dikelilingi oleh cekungan besar dan tailing yang tak kunjung direklamasi, tempat itu terus-menerus mengingatkan warganya bahwa tanah mereka mungkin tidak akan kembali seperti dulu.
Saya melihat tanah yang dulu mungkin hutan, mungkin kebun, mungkin ladang yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Sekarang, tanah itu berubah menjadi cekungan yang tidak menawarkan apa pun selain ketidakpastian.
Perdebatan soal tambang sering kali disederhanakan menjadi dua kubu, seakan hanya ada pro dan kontra. Namun ketika seseorang berdiri di tepi lubang sebesar yang saya lihat belum lama ini, perdebatan itu menjadi jauh lebih kompleks.
Ini bukan lagi soal memilih pihak, tetapi soal keberanian untuk menatap kenyataan di mana ruang hidup di sekitar kita semakin menyempit, perlahan tapi pasti. Warga dipaksa menyesuaikan diri dengan lubang-lubang yang tidak pernah mereka minta, sementara pihak yang menggali dapat berpindah ke lokasi berikutnya tanpa harus menanggung konsekuensi jangka panjang.
Ada ironi pahit yang sulit diabaikan di sana. Mereka yang mengubah lanskap dapat pergi kapan saja, tetapi mereka yang tinggal harus menghadapi perubahan itu setiap hari.
Ketika berbicara tentang tambang di Kaltim, kita tidak sedang membahas satu lubang besar yang berdiri sendiri, tetapi sebuah pola. Pola yang menunjukkan bagaimana tanah diperlakukan sebagai sumber daya yang bisa dibuka dan ditinggalkan kapan saja.
Lubang-lubang yang tidak direklamasi tepat waktu bukan hanya menyisakan bahaya ekologis, tetapi juga bahaya sosial. Lokasi-lokasi itu dapat menjadi kolam tak terduga saat hujan, dapat menjadi tempat rawan kecelakaan, dan dalam banyak kasus, menjadi simbol ketidakpedulian terhadap masyarakat lokal.
Realitas ini bukan hal baru bagi warga Kaltim, namun tetap terasa menyesakkan ketika melihatnya langsung.
Setelah melihatnya sendiri, saya memahami bahwa sulit untuk berpura-pura tidak tahu. Saya memahami mengapa banyak warga merasa bahwa tanah tempat mereka tinggal semakin lama semakin menyusut. Bukan karena erosi alami, tetapi karena keputusan-keputusan yang dibuat jauh dari rumah mereka.
Saya memahami mengapa orang-orang khawatir, tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga soal identitas tempat tinggal mereka. Sebuah desa kehilangan lebih dari sekadar tanah ketika tambang meninggalkan lubang raksasa.
Ia kehilangan memori kolektif, kehilangan orientasi ruang, bahkan kehilangan hak untuk bermimpi tentang masa depan yang stabil.
Opini ini ditulis bukan untuk menawarkan solusi teknis, bukan untuk menuduh atau menghakimi, tetapi untuk menyampaikan satu hal sederhana yang sering luput dari narasi besar tentang industri: apa yang dilihat langsung oleh warga jauh lebih penting daripada apa yang dicatat dalam laporan tahunan.
Pengalaman melihat sebuah lubang tambang raksasa membuat saya sadar bahwa kerusakan lingkungan bukan istilah abstrak. Hal itu berwujud nyata, besar, dalam, dan berada sangat dekat dengan kehidupan orang banyak.
Dan jika suara mereka yang melihat langsung tidak didengar, maka kerusakan itu akan terus dianggap biasa, seakan-akan tanah yang hilang hanyalah bagian kecil dari proses pembangunan.
Satu hal yang tidak dapat saya lupakan adalah rasa hening yang menggantung di atas lubang itu. Hening yang terasa seperti peringatan.
Bukan sekadar peringatan bahwa tanah telah berubah, tetapi bahwa waktu akan terus berjalan dan lubang itu akan tetap ada jika tidak ada upaya untuk memulihkannya. Kita sering diajarkan bahwa pembangunan harus membawa harapan.
Tetapi apa artinya pembangunan jika meninggalkan lubang-lubang yang bahkan generasi berikutnya tidak bisa mengatasi tanpa beban?
Pada akhirnya, berdiri di tepi lubang tambang itu membuat saya menyadari bahwa suara kita perlu lebih keras daripada mesin yang menggalinya. Bukan untuk menolak setiap bentuk industri, tetapi untuk menuntut tanggung jawab yang setara dengan kerusakan yang ditinggalkan.
Jika tanah bisa berbicara, mungkin ia akan mengatakan hal yang sama. Namun karena tanah diam, maka manusialah yang harus bersuara. Dan selama lubang-lubang itu masih menganga tanpa rencana pemulihan yang jelas, suara itu tidak boleh padam.
Tambang selalu dibungkus dengan narasi pembangunan, lapangan kerja, kontribusi ekonomi. Tetapi jarang ada yang berbicara jujur tentang sisi lain yang tidak tercatat dalam laporan tahunan; hilangnya rasa aman warga, hilangnya ruang publik alami, hilangnya hubungan orang dengan tanah yang mereka injak. Sering kali, kerugian terbesar bukan dinilai dari uang, tapi dari hilangnya sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali.
Dan mungkin itu alasan mengapa pengalaman melihat lubang raksasa itu begitu mengganggu. Lubang itu adalah pengingat kasar bahwa apa pun yang kita baca tentang tambang tidak akan pernah sebanding dengan melihat bekasnya yang nyata.
Bahwa setelah semua keuntungan diambil, yang tertinggal sering kali hanya beban yang harus ditanggung oleh orang-orang yang tidak ikut memutuskan apa-apa.
Pada akhirnya, suara warga mungkin tidak bisa menutup lubang yang sudah terlanjur menganga. Tapi suara itu bisa mencegah lubang baru muncul tanpa pertanggungjawaban. Suara itu bisa menahan laju yang terlalu liar, terlalu rakus, terlalu cepat.
Dan opini seperti ini hanyalah bagian kecil dari suara itu, suara yang berkata bahwa bumi bukan hanya tempat yang bisa digali sesuka hati, tetapi rumah yang seharusnya dijaga sebelum semuanya terlambat.
Opini ini ditulis oleh Sabrina, mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unmul 2024