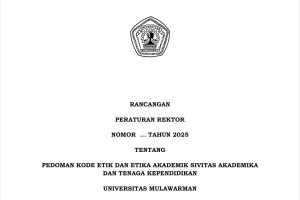Sumber Gambar: Pasundan Ekspres
SKETSA – Fenomena pernikahan usia muda belakangan ini sedang hangat diperbincangkan di media sosial. Ini bermula dari sebuah wedding organizer (WO) yang mempromosikan pernikahan di usia muda. Berdasarkan materi promosinya, WO Aisha ini diketahui mengampanyekan menikah di usia 12-21 tahun. Tentunya, ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana disebutkan, usia minimal pasangan menikah adalah 19 tahun.
Irma Suriyani, salah satu dosen Fakultas Hukum (FH) Unmul memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut. Menurutnya, pernikahan usia dini dinilai tidak relevan jika dilihat dari perkembangan zaman dan memberikan dampak negatif kepada anak. Karenanya, undang-undang mengenai pernikahan diperbaiki.
“Karena perkembangan zaman dan peradaban manusia, pernikahan yang awalnya rata-rata pada umur 10-12 tahun, dianggap membawa masalah-masalah yang banyak. Salah satunya yaitu hak kesehatan, hak reproduksi, hak sosial, hak ekonomi dan hak pendidikan,” ujarnya saat dihubungi Sketsa pada Senin, (22/2).
Ia juga memaparkan contoh lain terkait kasus ini. Perbedaan budaya terdahulu yang tidak dituntut untuk berpendidikan tinggi seperti sekarang misalnya. Itulah yang kemudian melahirkan suatu hukum. Berubahnya suatu hukum disebabkan oleh berubahnya peradaban dan hal ini berkaitan dengan adanya masalah pernikahan dini.
Tak hanya itu, Irma menambahkan bahwa penerapan peraturan mengenai pernikahan anak ini sulit untuk diterapkan karena ada regulasi hukum yang tumpang tindih. Menurutnya, terlalu muda jika diperbolehkan menikah di rentang usia tersebut dan di anggap melanggar UU Perlindungan Anak.
“Padahal dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa anak yang masih berada dalam usia kandungan, dari 0-18 tahun itu masuk dalam kategori usia anak. Sementara, di UU Perkawinan diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun, padahal itu masih dalam batas usia anak. Ada kontradiktif akan ketidakseragaman antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan yang mengatur batas usia menikah,” jelasnya.
Dari sisi Sosiologi, dosen Program Studi Pembangunan Sosial Sri Murlianti menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pernikahan anak cenderung berbeda antar kasus di kampung dan perkotaan.
“Faktor penyebab pertama adalah masalah ekonomi dianggap sebagai penyelesaian pintas. Faktor lain adalah kurangnya akses pendidikan dan informasi yang baik. Sehingga wawasan tentang hak-hak anak masih sangat terbatasn. Ini untuk wilayah perkampungan. Untuk wilayah perkotaan, biasanya dipicu oleh pergaulan bebas, kurang pengawasan orang tua atau pengaruh gagdet,” tukasnya, Jumat (26/2).
Hariani Lubis, dosen Psikologi Unmul yang satu ini juga berkomentar mengenai dampak negatif dari pernikahan anak.
“Banyak sekali dampak negatif yang mungkin bisa ditimbulkan dari pernikahan anak. Yang pertama dari segi perkembangan fisik. Kan organ reproduksi anak belum berkembang dengan matang, belum berkembang dengan sempurna. Nah, jadi bisa menyebabkan penyakit misalnya kanker serviks,” terangnya saat dihubungi melalui WhatsApp pada Sabtu, (20/2).
Selain dampak fisik, ia juga menjelaskan dampak pernikahan anak dari segi mental. Menurutnya, emosi yang belum stabil juga akan berpengaruh kepada pasangan suami istri dan rentan bertengkar lalu memicu pertengkaran. Ia beranggapan, pada usia tersebut anak masih kurang mampu untuk mengendalikan emosi. Cara berpikirnya masih egosentris dan masih egois. Sehingga ketika dihadapkan pada permasalahan dalam rumah tangga, mereka kurang mampu mencari solusi yang logis.
Baginya, semua pihak terkait seharusnya dapat ikut berperan dalam mencegah pernikahan anak. Mulai dari keluarga, pemerintah, pemuka agama hingga tenaga ahli seperti dokter dan psikolog. Di samping itu, orang tua juga harus berperan penting untuk meningkatkan keberfungsian keluarga dalam pengasuhan.
Ia melanjutkan, edukasi mengenai seks untuk anak dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini. Ini perlu agar anak mengetahui batasan-batasan dalam pergaulannya. Sehingga ketika mencapai usia remaja, mereka tahu bagaimana harus bersikap dengan lawan jenis dan membatasi pergaulan.
Selain itu, perlu ada peningkatan terkait pemahaman kepada masyarakat. Khususnya mengenai dampak negatif pernikahan anak, karena masih banyak nilai-nilai budaya yang melekat di masyarakat mengenai pernikahan anak. Di samping itu, perjodohan masih sangat sering terjadi. Maka, perlu dilakukannya sosialisasi dan edukasi bahwa pernikahan anak menimbulkan dampak yang negatif. (hdt/bey/ash/lyn/fzn)