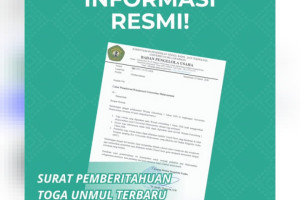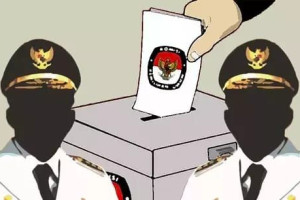Retorika di Layar, Luka di Jalanan (Analisis Video Ungkapan Keprihatinan Presiden Prabowo, 28 Agustus 2025)
Pidato Prabowo pascademo dinilai penuh retorika, minim empati, dan abai substansi tuntutan rakyat
- 03 Sep 2025
- Komentar
- 1047 Kali

Sumber Gambar: Instagram @kemensetneg.ri
Pecahnya demonstrasi besar di Jakarta, Kamis (28/8) yang menelan banyak korban jiwa, termasuk tewasnya seorang pengemudi ojek online, memicu gelombang kemarahan dan aksi susulan di berbagai daerah. Situasi yang kian panas tidak hanya menandai krisis sosial, tetapi juga memperlihatkan rentannya ruang aman bagi warga dalam menyuarakan aspirasi. Di tengah ketegangan yang masih berlangsung, tepat pada jam malam hari itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo melalui akun sosial media resmi pemerintah dan pejabat di bawahnya merilis sebuah video ucapan belasungkawa.
Namun, isi video tersebut justru menimbulkan pertanyaan di tengah publik. Apakah ia dapat disebut sebagai pidato kenegaraan, sekadar ucapan belasungkawa, atau hanya narasi penenang sesaat?
Pesan yang disampaikan tampak terlalu netral dan berhati-hati, bahkan cenderung menghindari substansi persoalan yang melatarbelakangi aksi demonstrasi. Alih-alih menunjukkan arah yang jelas atau empati yang kuat, ucapan itu terasa datar dan minim respons terhadap inti peristiwa yang tengah melukai nurani publik, yang kemudian ditutup dengan retorika optimisme presiden dan pemerintah yang terkesan narsistik dan defensif.
Apa yang sebenarnya ingin disampaikan?
Dalam menganalisis isi pidato presiden, digunakan metode gabungan antara N-gram dan Analisis Diskriminan Linier (LDA). Berikut adalah jumlah frekuensi kata unik dan berulang:

Gambar 1 Diolah Penulis
Dari tabel diatas, kata “bangsa, negara, pemerintah, petugas” menjadi kata yang sering muncul. Hal ini menunjukkan orientasi state-centered, yang lebih fokus pada citra negara ketimbang empati personal. Sedangkan kata “ambil tindakan, usut tuntas, ojol (Afan Kurniawan), sedih, dll” memperlihatkan ada respons hukum, tapi hanya sekilas muncul dan tidak dominan sebagai bentuk respons jatuhnya korban. Pidato atau narasi yang disampaikan Presiden Prabowo, dalam konteks ini tampak lebih menekankan legitimasi negara ketimbang mendengar substansi kritik massa aksi.
Dalam konteks ini, pidato atau narasi yang disampaikan Presiden Prabowo lebih menonjolkan upaya legitimasi negara melalui penekanan pada hukum, ketertiban, dan pembangunan nasional, ketimbang memberikan ruang yang nyata bagi substansi kritik massa aksi.
Kalimat seperti “seandainya ditemukan petugas berbuat di luar kepatutan akan diambil tindakan sekeras-kerasnya” sekilas terlihat tegas, tetapi justru mengaburkan fakta bahwa insiden sudah terang terjadi di lapangan, yakni petugas menabrak dan melindas pengemudi ojol. Dengan mengemasnya seolah masih menunggu pembuktian, pidato ini gagal memberi pengakuan penuh pada kesalahan aparat.
Seruan untuk “percaya kepada pemerintah yang saya pimpin” juga memperlihatkan kontradiksi. Permintaan itu datang di tengah sejarah singkat kepemimpinannya yang sarat dengan kontroversi aparat dan kebijakan bermasalah. Alih-alih membangun kepercayaan lewat langkah konkret, presiden justru meminta publik menyerahkan kepercayaannya tanpa dasar yang kuat.
Demikian pula himbauan agar masyarakat “waspada terhadap unsur yang ingin membuat huru-hara” lebih terdengar sebagai framing massa aksi sebagai ancaman, bukan sebagai rakyat yang sedang menyampaikan kritik. Alih-alih menenangkan, kalimat ini justru memanaskan suasana dengan memposisikan negara sebagai korban.
Narasi pembangunan yang kemudian diusung, “bangsa kita sedang berbenah, membangun negara kuat, maju, mandiri, sejahtera” pada akhirnya tampak seperti pengalihan isu. Dalam konteks tuntutan aksi, publik justru mempertanyakan kebijakan yang nyata bermasalah: Program Makan Bergizi Gratis yang menuai kasus keracunan dan dugaan korupsi, kesejahteraan guru yang diabaikan, eksploitasi tambang yang kian masif, hingga kesepakatan ekonomi-politik dengan pihak asing yang tidak berpihak pada warga. Retorika industrialisasi dan janji menekan kemiskinan pun berbanding terbalik dengan realitas meningkatnya PHK akibat efisiensi anggaran dan naiknya angka pengangguran.
Dengan demikian, pidato presiden lebih berfungsi sebagai respons simbolik ketimbang substantif. Ia menghadirkan wajah negara yang tegas dan penuh retorika kebangsaan, tetapi mengabaikan inti masalah yakni, keadilan bagi korban, keterbukaan pada kritik, dan solusi atas kegagalan kebijakan. Alih-alih meredam ketegangan, pidato semacam ini justru berpotensi memperlebar jarak kepercayaan antara negara dan rakyat.
Pidato seperti ini di tengah aksi massa menunjukkan dilema klasik antara memilih stabilitas atau membuka ruang kritik. Sayangnya, dalam kasus ini, narasi stabilitas lebih menonjol ketimbang komitmen demokratis. Jika demokrasi ingin tetap hidup, presiden dan para pemimpin negara perlu belajar bahwa aksi massa bukan ancaman, melainkan bagian dari denyut nadi demokrasi itu sendiri. Alih-alih membungkam, negara semestinya menjadikan kritik sebagai energi korektif untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.
Diamnya presiden sebagai eksekutif yang tidak bertaring terhadap tindak tanduk legislatif, menunjukkan check and balances lagi-lagi tidak berjalan. Mungkin menjadi tidak aneh karena komposisi dewan yang terbentuk saat ini tidak lain berasal dari lumbung koalisi yang sama dengan presiden. Lagi-lagi, demokrasi tanpa ruang aman bagi kritik hanyalah prosedur tanpa substansi.
Opini ini ditulis oleh Afizah Nur Afkarina, mahasiswi FH Unmul 2021