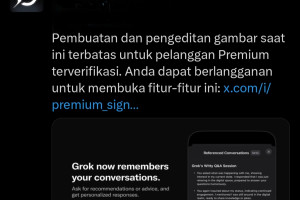Ketika Prosedur Mengalahkan Substansi, KHDTK Unmul Jadi Korban
Kasus KHDTK Unmul tunjukkan hukum tumpul pada kejahatan lingkungan
- 19 Sep 2025
- Komentar
- 1075 Kali

Sumber Gambar: Website kaltimtoday.co
Putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka Daria dan Eddy dalam kasus perambahan kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul menimbulkan pertanyaan besar tentang wajah penegakan hukum lingkungan di negeri ini.
Pertanyaannya sederhana: Mengapa dua orang yang secara jelas diduga berperan dalam kegiatan tambang ilegal bisa lolos dari jerat hukum hanya karena persoalan prosedur?
Sejak awal, kasus ini bukan sekadar soal pelanggaran administratif. Ini tentang bagaimana sebuah kawasan hutan pendidikan, yang seharusnya steril dari aktivitas industri ekstraktif, justru menjadi sasaran pembongkaran dan perusakan.
KHDTK bukan milik individu atau korporasi. Ia adalah milik publik. Lebih dari itu, ia adalah simbol masa depan pendidikan kehutanan Indonesia.
Publik dikejutkan ketika alat berat ditemukan beroperasi di KHDTK pada awal April 2025. Mahasiswa dan pengelola fakultas menyuarakan penolakan keras, KLHK turun tangan, dan penyidikan dimulai.
Lalu muncul nama Daria, direktur perusahaan yang diduga menyewa alat berat, dan Eddy, operator lapangan yang mengkoordinasi aktivitas tambang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, dan diperiksa.
Semua tampak berjalan sesuai harapan, sampai akhirnya pengadilan membatalkan penetapan tersangka tersebut melalui jalur praperadilan.
Alasan yang digunakan? Masalah prosedural. Misalnya, ketiadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta cacat administratif lainnya.
Hukum acara memang penting. Namun, ketika substansi pelanggaran begitu jelas, alat berat ditemukan, saksi diperiksa, kawasan rusak, maka pembatalan semacam ini lebih mencerminkan kelemahan sistem hukum daripada perlindungan terhadap hak asasi tersangka.
Dalam teori hukum, praperadilan adalah mekanisme penting untuk melindungi warga dari kriminalisasi. Namun dalam praktik, ia bisa menjadi “senjata hukum” untuk menggugurkan perkara atas dasar teknis administratif meskipun substansi pelanggaran begitu terang benderang.
Ketika kerusakan hutan telah terverifikasi seluas 3,26 hektare, sangat mengherankan bahwa celah prosedur bisa menjadi tiket kebebasan bagi orang-orang yang diduga bertanggung jawab.
Penting untuk dicatat: Hutan yang dirusak tidak bisa mengajukan praperadilan. Satwa yang terusir tak punya kuasa hukum. Mahasiswa dan akademisi yang kehilangan ruang belajar tidak memiliki forum untuk menguji hak mereka. Tapi tersangka bisa.
Inilah ketimpangan struktural dalam sistem hukum kita. Hukum yang berpihak pada individu yang punya kuasa legal, bukan pada entitas yang rusak dan tak bisa bersuara.
Jika kita melihat lebih luas, kasus KHDTK Unmul hanyalah satu titik kecil dalam peta nasional penambangan ilegal yang tersebar luas. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, hingga 2021, ada 2.741 titik tambang ilegal (PETI) di seluruh Indonesia, termasuk 96 titik batu bara dan 2.645 titik tambang mineral lainnya. Dan angka ini terus bertambah.
Di Sumatera Barat, hampir 7 ribu hektare hutan rusak akibat tambang emas ilegal hanya dalam satu tahun. Di Aceh Barat, kerusakan mencapai lebih dari enam ratus hektare per tahun.
Bahkan di Nagan Raya, mencapai 972 hektare dalam waktu dua tahun. Tambang ilegal juga ditemukan tak jauh dari Ibu Kota Negara (IKN), dan menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp5,7 triliun.
Kerusakan ekologis ini bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tapi juga menghancurkan ekosistem, mengancam masyarakat lokal, dan menimbulkan konflik sosial. Sayangnya, banyak dari pelaku tambang ilegal ini juga menggunakan celah hukum untuk bebas dari jeratan pidana.
Putusan praperadilan ini memberi pesan yang salah kepada publik: Bahwa aktor-aktor yang punya modal, jaringan, dan kekuatan bisa lolos. Bukan karena tidak bersalah, tetapi karena penyidik tidak cukup rapi secara administratif.
Di sisi lain, hutan yang rusak tidak bisa membela dirinya sendiri. Ia bisu. Ia hanya bisa menunggu, siapa yang sudi memperjuangkannya.
Hari ini, KHDTK Unmul jadi korban. Besok mungkin hutan adat, taman nasional, atau kawasan konservasi lainnya. Lama-lama kita bisa kehilangan semua bukan hanya karena tambang, tapi karena hukum yang tumpul terhadap kejahatan lingkungan, namun tajam untuk prosedur.
Sebagai mahasiswa, akademisi, dan warga negara, kita tidak boleh diam. Kasus ini adalah ujian nyata apakah hukum kita berpihak pada keadilan ekologis atau sekadar tunduk pada administrasi dan celah teknis. KHDTK Unmul adalah milik bersama. Jika kita tak menjaganya, siapa lagi?
Opini ini ditulis oleh Cherin Sahdina Putri, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH Unmul 2024