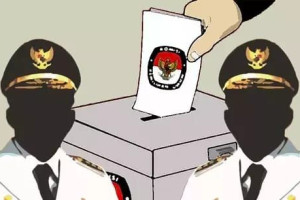Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
Dalam kehidupan bernegara, pemangku kebijakan (Baca: Kekuasaan) wajib mempunyai otoritas dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Tanpa otoritas, ia tidak dapat tampil di depan publik sembari mendeklarasikan bahwa dirinyalah yang akan menjadi penentu kesejahteraan kehidupan orang banyak.
Apabila bersikeras bertindak demikian, tentulah ia hanya akan menjadi bahan olokan dan diabaikan oleh orang-orang yang diklaim sebagai subjeknya. Oleh karenanya, suatu otoritas harus disandarkan pada suatu wacana yang dapat menjustifikasi klaim bahwa seseorang atau suatu kelompok tersebutlah yang layak mengatur hidup khalayak ramai.
Berbagai paham wacana yang dikembangkan oleh para teoritikus politik diambil dan dijadikan justifikasi oleh suatu grup dalam mengambil alih dan mengimplementasikan kekuasaan. Wacana yang dimaksud dapat didasarkan ke berbagai hal seperti wacana mandat dari Ilahi (teokratis), rakyat (demokratis), kelas bangsawan (monarkis), kelas pekerja (sosialis), dan sebagainya.
Dalam studi kasus Negara Indonesia, wacana mandat dari rakyat (demokrasi) digunakan sebagai landasan otoritas penguasa. Wacana yang tak jauh dari slogan “oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat” diargumentasikan dapat menjadi pemersatu suara untuk menjembatani kemajemukan masyarakat Indonesia. Di mana tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa memandang latar belakang sosial tiap individu. Namun dalam implementasinya, negara kerap membatasi hak-hak tersebut tanpa mengkompromi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara.
Hak-hak berupa kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, berserikat, serta memperoleh ilmu dan pendidikan tak jarang diberangus oleh negara jika kegiatan tersebut berseberangan dengan kepentingan penguasa yang sedang menjabat. Rangkaian pelanggaran tersebut menjadi corak Pemerintah Indonesia pada saat rezim orde baru (Orba) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966 - 1998.
Pelanggaran-pelanggaran itulah yang menjadi latar alur dari novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Novel tersebut mengikuti kisah seorang mahasiswa bernama Biru Laut dan teman-teman perkuliahannya dalam perlawanan mereka melawan rezim orde baru.
Mulai dari mengawal penanganan konflik agraria antara petani dan militer sampai mempublikasi tulisan-tulisan kritis akan kondisi sosial-politik yang sedang dialami oleh Indonesia, Laut dan kawan-kawannya menghadapi berbagai rintangan dan tindakan represif dari aparat kenegaraan. Novel tersebut juga diwarnai dengan tema-tema seperti persahabatan, percintaan, dan pengkhianatan yang dialami oleh Laut dan kawan-kawannya.
Dari novel tersebut dapat kita sadari bahwa tindakan pelanggaran hak-hak kewarganegaraan masih menjadi isu yang tak pernah padam bahkan sampai saat ini di mana Indonesia sudah melewati rezim orde baru dan sedang dalam masa reformasi. Pembungkaman akan hal-hal yang dianggap menentang kestabilan (Baca: Kepentingan) yang sudah berlaku masih kerap terjadi seakan-akan ada nostalgia tersendiri akan sikap-sikap rezim orde baru.
Isu terbaru perihal pembungkaman demi kepentingan terjadi di Pulau Rempang. Kabarnya, di pulau tersebut akan dibangun Eco-City yang memakan lahan sekitar 2.000 hektar. Demi tersedianya lahan tersebut, rumah-rumah warga lokal terancam digusur tanpa adanya sosialisasi maupun negosiasi kompensasi terlebih dahulu.
Para warga yang menolak rencana tersebut menyuarakan aspirasi mereka melalui demonstrasi yang disambut oleh lebih dari seribu aparat bersenjata lengkap. Pembubaran massa dilakukan dengan penembakan gas air mata secara membabi buta hingga selongsong gas air mata pun ada yang jatuh di area sekolah.
Tak berhenti sampai di situ saja, aparat juga melakukan taktik intimidasi terhadap warga lokal dengan melakukan patroli tanpa adanya kepentingan dan mendirikan pos-pos “keamanan” di sekitar pemukiman warga. Sampai dengan ditulisnya artikel ini, belum ada titik temu antara para warga setempat dengan pemerintah terkait nasib mereka dan tanah leluhur mereka kedepannya.
Dalam lingkup yang lebih kecil, kejadian yang senada terjadi di Unmul. Pada tanggal 3 Agustus 2023, agenda Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan oleh pihak universitas dalam rangka menyambut mahasiswa baru. Dalam agenda yang seharusnya dihadiri 13 fakultas, FISIP tidak mengirimkan mahasiswa baru (maba) yang berjumlah 658 orang dalam agenda tersebut.
Tindakan tersebut diambil oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (MPM FISIP), sebagai lembaga tertinggi mahasiswa FISIP Unmul, dikarenakan fasilitas PKKMB yang tidak memadai dan beberapa isu kampus lain yang, menurut mereka, belum terselesaikan oleh pihak birokrat Unmul pada saat itu.
Atas tindakan tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unmul sekaligus Ketua Panitia PKKMB Unmul tahun 2023, Moh. Bahzar, memberi tanggapan reaktif dengan memohon kepada Rektor Unmul untuk memberi sanksi yang berat kepada FISIP.
Ditambah lagi, beliau juga mengancam akan membekukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP karena ikut serta dalam keputusan MPM FISIP Unmul. Kendati demikian, sampai dengan ditulisnya artikel ini, belum ada keputusan resmi dari pihak Rektorat Unmul dalam menanggapi aksi yang dilakukan oleh MPM FISIP maupun pernyataan dari WR III Unmul.
Kedua kejadian di atas hanyalah sedikit contoh dari banyaknya kasus pembungkaman yang dilakukan oleh pihak pengampu kebijakan (baca: kekuasaan) terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu kepentingan mereka. Mirisnya lagi, dalam contoh kasus PKKMB Unmul, bahkan pihak kampus yang mengklaim dirinya sebagai miniatur negara dan seharusnya menjadi mercusuar reformasi untuk menuju ke pelabuhan demokrasi Negara Indonesia justru melakukan tindakan-tindakan yang bernuansa represif ala orde baru.
Jika dikorelasikan antara apa yang terjadi di Pulau Rempang dengan kejadian saat PKKMB Unmul tahun 2023, warga lokal dan aparat pemerintahan membiaskan bayangan semu di Unmul dalam bentuk MPM FISIP Unmul dan WR III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, respectively
Dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak-hak yang dijamin konstitusi hanya ada satu solusi, yaitu: menaati peraturan yang sebelumnya dilanggar. Hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat, yang tertuang dalam pasal 28 E ayat 3, haruslah ditaati dan dihormati tanpa kompromi.
Apabila terjadi pemberangusan hak-hak konstitusional warga negara oleh para pemangku kebijakan (baca: kekuasaan) dengan dalih demi keamanan dan kestabilan sosial, maka wajib dipertanyakan keamanan siapa dan kestabilan apa yang terganggu.
Logikanya ialah, jika warga negara menggunakan hak konstitusionalnya dan hal tersebut, menurut pemangku kekuasaan, mengganggu keamanan dan kestabilan sosial serta ditanggapi dengan represif, maka dapat disimpulkan bahwa keamanan dan kestabilan ini diciptakan oleh pemangku kekuasaan dengan cara-cara dan/atau tujuan yang inkonstitusional. Dengan kata lain, keamanan dan kestabilan sosial yang dimaksud oleh pemangku kekuasaan tidak sejalan dengan tujuan berdirinya negara itu sendiri.
Opini ditulis oleh Zain Aqil Hidayat, Koordinator Komunitas Laboratorium Intelektual Humanawa