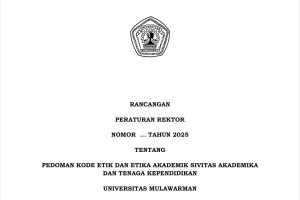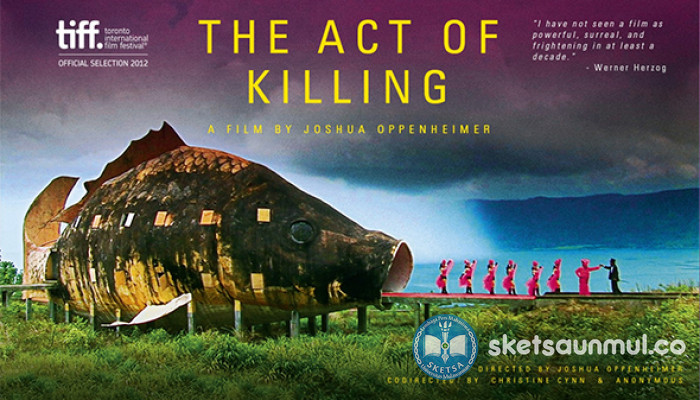
Jurnal Footage
“Bayangkan jika para pelaku kekerasan menceritakan kisah mereka sendiri, bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan kebanggaan.” Kalimat ini seolah menggambarkan dengan tepat sajak-sajak History Cinema yang diselenggarakan oleh Departemen Kajian dan Keilmuan (KAIL) Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS).
Pada Selasa (30/9) acara nonton bareng film Jagal (2012) ini menjadi salah satu program kerja departemen yang rutin diadakan, bertepatan dengan momen refleksi sejarah nasional, yaitu peringatan peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Dengan tema “Membaca Luka Bangsa Lewat Layar,” acara ini menghadirkan diskusi hangat bersama Zulkifli Randa, yang merupakan dosen program studi Pendidikan Sejarah FKIP Unmul. Diskusi ini mengajak mahasiswa untuk menelusuri sejarah Indonesia dari sisi yang sering terlupakan: sisi pelaku, sisi propaganda, dan sisi kemanusiaan.
Suasana malam itu terasa khidmat namun hangat. Lampu dimatikan, layar menyala, dan para mahasiswa fokus menatap tayangan. Beberapa mencatat, sebagian lainnya hanya terdiam, seolah sedang berdialog dengan hati nurani mereka sendiri. Film Jagal bukan tontonan ringan. Ia tentang bagaimana manusia bisa membungkus kekerasan menjadi kebanggaan.
Film dokumenter Jagal (The Act of Killing) karya sutradara Joshua Oppenheimer mengangkat kisah kelam Indonesia pasca peristiwa 1965-1966. Namun, alih-alih menyoroti korban, film ini justru menampilkan para pelaku pembunuhan massal yang dengan bangga menceritakan kembali bagaimana mereka menghabisi ribuan nyawa. Dengan pendekatan yang unik, Oppenheimer meminta para pelaku untuk memerankan ulang aksi mereka, bahkan dengan gaya film favorit mereka masing-masing, mulai dari film gangster hingga musikal.
Hasilnya sungguh menggetarkan: penonton dipaksa menyaksikan bagaimana kekerasan bisa tampak seperti kebanggaan, bagaimana propaganda mampu menumpulkan empati. Jagal bukan sekedar dokumenter, tetapi juga cermin yang memantulkan sisi tergelap dari sejarah bangsa dan sekaligus dari diri manusia itu sendiri.
Melalui film ini, Oppenheimer tidak hanya menunjukkan sisi kejam dari peristiwa 1965, tetapi juga mengajak kita merenung tentang bagaimana kekuasaan dapat menghapus rasa bersalah. Dalam satu adegan, seorang pelaku tampak bangga menceritakan cara ia membunuh, lalu di akhir film terlihat terguncang ketika akhirnya menyadari beban moral dari tindakannya. Momen itu menjadi simbol bahwa kebenaran mungkin bisa ditutupi, tapi tidak bisa dihapus selamanya.
Peristiwa 1965-1966 sendiri merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Ratusan ribu orang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) tanpa proses hukum yang jelas. Mereka ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh.
Selama puluhan tahun, kisah mereka dibungkam. Maka ketika Jagal hadir, ia seakan membuka kotak pandora sejarah yang selama ini dikunci rapat oleh kekuasaan.
Setelah film berakhir, ruangan sempat hening cukup lama. Beberapa mahasiswa mengaku merasa tidak nyaman hingga mual, menyaksikan adegan-adegan yang direka ulang dengan begitu apik. Namun dari ketidaknyamanan itu muncul perenungan baru.
Salah satu peserta diskusi berkata, “Saya jadi sadar, sejarah itu bukan cuma tentang siapa benar dan siapa salah, tapi tentang bagaimana kekuasaan membentuk kebenaran.”
Seperti yang disampaikan oleh Zulkifli Randa dalam diskusi pasca pemutaran “fakta sejarah itu bagaikan kamera, siapa yang memegang kamera, maka sudut pandang itulah yang akan mendominasi.” Selama Orde Baru, kamera sejarah dipegang sepenuhnya oleh rezim.
Narasi tentang PKI dibangun secara sistematis untuk menumbuhkan ketakutan dan kebencian. Propaganda dijalankan melalui berbagai cara, seperti film wajib tonton Penumpasan Pengkhianatan G30S, media, buku pelajaran, hingga monumen dan museum yang hanya menampilkan satu versi kebenaran, dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Generasi tumbuh dengan rasa takut terhadap simbol palu arit tanpa pernah memahami konteks sejarah di baliknya.
Selama lebih dari tiga dekade, narasi itu tertanam dalam benak masyarakat, membentuk ketakutan kolektif yang masih terasa hingga kini. Anak-anak keturunan PKI mengalami diskriminasi, sulit mengakses pendidikan, pekerjaan, bahkan pernikahan. Semua itu lahir dari satu hal sejarah yang diceritakan dari satu sisi saja. Dalam konteks ini, film Jagal menjadi penting bukan karena ia “membenarkan” PKI, tetapi karena ia membuka ruang bagi kita untuk melihat peristiwa 1965 dari perspektif lain, tanpa dikekang narasi tunggal. Ia mengajak penonton menilai ulang, siapa sebenarnya yang berkuasa dalam membentuk sejarah?
Sebagai calon pendidik, mahasiswa sejarah diajak merenung, dihadapkan pada tantangan besar, bagaimana kita akan mengajarkan peristiwa seperti 1965 kepada siswa di masa depan? Apakah kita hanya akan mengulang narasi lama, atau membuka ruang berpikir kritis bagi peserta didik?
Zulkifli Randa menegaskan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai ruang kritis, bukan ruang doktrinasi. Sejarah harus diajarkan sebagai ruang berpikir, bukan ruang menghakimi.
“Jangan sampai emosi dan kebencian dibawa ke ruang kelas. Sejarah seharusnya menjadi alat berpikir, bukan alat menanamkan dendam”.
Pernyataan ini menjadi refleksi penting bagi penonton. Sebagian mahasiswa mengungkapkan bahwa selama ini mereka terbiasa menghafal fakta sejarah, bukan memahaminya secara kritis. Setelah menonton Jagal, mereka menyadari bahwa sejarah adalah proses interpretasi, bukan kumpulan tanggal dan nama tokoh semata.
Dalam konteks ini, teori Taksonomi Bloom pun menjadi relevan di sini guru harus menyesuaikan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu “apa yang terjadi” tetapi juga bisa bertanya “mengapa itu bisa terjadi.” Selain itu mereka juga bisa memahami sejarah sebagai hasil interpretasi, bukan kebenaran tunggal.
Film seperti Jagal membantu kita memahami serta menjadi sarana refleksi yang efektif, bahwa sejarah tidak hanya milik pemenang. Ia juga milik korban, saksi, bahkan pelaku. Ketiganya membentuk mosaik masa lalu yang utuh dan dari situlah kita belajar empati.
Sebagai mahasiswa sejarah, penulis merasa film ini seperti tamparan halus. Kita sering kali mempelajari sejarah dari buku yang rapi dan teratur, padahal di balik setiap paragraf ada darah, air mata, dan trauma yang nyata. Melihat para pelaku berbicara dengan bangga membuat saya bertanya-tanya: apakah manusia benar-benar belajar dari masa lalunya?
Peristiwa 1965 bukan hanya tentang konflik ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Ia adalah cermin bagaimana kekuasaan dapat menghapus rasa bersalah dan memanipulasi moralitas, dan juga tentang manipulasi narasi dan hilangnya rasa kemanusiaan. Para pelaku kekerasan dalam Jagal menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat menghapus rasa bersalah, dan bagaimana manusia bisa kehilangan empati karena keyakinan bahwa mereka sedang “membela negara”.
Namun, momen paling emosional justru muncul dalam film terjadi ketika salah satu pelaku akhirnya terdiam dan muntah setelah menceritakan kembali aksinya. Dalam sekejap, penonton disadarkan bahwa di balik kesombongan itu, ada rasa bersalah yang tidak bisa dihapus oleh ideologi, ia hanya bisa ditekan, tetapi tetap hidup dalam batin manusia.
Melalui film ini, dan diskusi yang mengiringinya, menunjukkan betapa pentingnya menonton sejarah dengan mata terbuka. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Karena memahami bukan berarti membenarkan, tetapi memahami bagaimana manusia bisa terjebak dalam sistem kekuasaan yang menipu nurani. Film ini juga mengingatkan kita bahwa rekonsiliasi tidak mungkin terjadi tanpa kejujuran.
Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, ia hidup dalam cara kita berpikir, mengajar, dan memandang sesama, ia tidak pernah benar-benar usai. Melalui film Jagal, kita belajar bahwa kebenaran sejarah tidak tunggal. Ia adalah hasil dari banyak suara, termasuk suara yang selama ini dibungkam, dan tugas kita adalah mendengarkannya.
Dari kegiatan ini sebagai mahasiswa sejarah dan generasi muda berarti menjadi penjaga ingatan kolektif. Tugas kita bukan melanjutkan narasi lama, melainkan membangun kesadaran baru bahwa sejarah harus menjadi ruang dialog, bukan ruang propaganda. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menutup luka masa lalunya, melainkan yang berani merawatnya dengan jujur, luka masa lalu hanya bisa sembuh jika kita berani menatapnya, bukan menutup mata.
Jagal bukan sekedar film, ia adalah pengingat bahwa kemanusiaan harus selalu menjadi pusat dari setiap pembacaan sejarah, dan juga peringatan bahwa bangsa yang lupa masa lalunya akan kehilangan kemanusiaannya. Menonton Jagal berarti menatap cermin bangsa dan di dalam cermin itu, kita melihat wajah kita sendiri. Melalui film ini, kita diajak untuk tidak sekadar menonton sejarah, tetapi menyembuhkannya dengan cara memahami.
Opini ini ditulis oleh Hilda Herawati, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unmul 2024