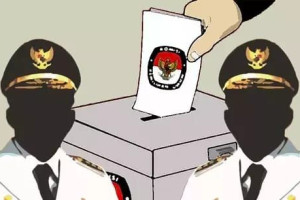Sumber Gambar: Pexels
Setiap pagi, banyak dari kita membuka ponsel bahkan sebelum benar-benar bangun. Bukan untuk hal penting, melainkan karena sudah menjadi kebiasaan. Dari notifikasi, lanjut ke video, lalu komentar. Tiba-tiba waktu berjalan tanpa terasa. Kebiasaan ini bukan lagi sekadar aktivitas ringan, tetapi sudah memengaruhi cara kita memulai hari.
Generasiku, generasi yang tumbuh bersama internet, hidup dalam arus informasi yang sangat cepat. Satu kali scroll langsung membawa kita ke hal yang berbeda, sampai-sampai pikiran tidak sempat memahami apa yang baru saja dilihat. Di balik kenyamanan itu, ada dampak yang mulai terasa. Kita jadi lebih mudah terdistraksi dan sulit mempertahankan fokus. Fenomena ini disebut juga dengan doom scrolling.
Data terbaru di Indonesia menunjukkan hal ini bukan sekadar perasaan. Survei Talker Research 2024 menemukan bahwa remaja Indonesia menghabiskan rata-rata 6,6 jam per hari di media sosial dan sekitar 11 persennya bisa menghabiskan lebih dari 15 jam. Penelitian lain pada remaja usia 13–19 tahun menunjukkan durasi penggunaan media sosial berkaitan dengan menurunnya kemampuan fokus saat belajar.
Studi tahun 2024 juga mencatat 82,3 persen remaja melakukan doom scrolling beberapa kali dalam seminggu. Kebiasaan itu berkaitan dengan kecemasan serta gangguan tidur. Artinya, masalahnya nyata dan sudah didukung temuan penelitian.
Saat kita scroll, otak merespons seperti orang yang kecanduan game judi online, yang selalu menunggu kejutan selanjutnya. Media sosial memang dirancang untuk membuat kita terus kembali. Setiap konten baru memberi dorongan kecil yang membuat kita penasaran dan ingin melihat lebih banyak. Lama-kelamaan, sulit untuk berhenti walaupun kita tahu sebenarnya sudah cukup.
Sebagai bagian dari Generasi Z (Gen Z), aku juga merasakan hal itu. Kadang sadar sedang kehilangan fokus, tetapi tetap lanjut scroll tanpa alasan jelas. Bukan karena butuh informasinya, tapi karena sudah terbiasa. Rasanya seperti otak tidak mau diam, padahal sebenarnya butuh istirahat.
Scroll sendiri tidak selalu negatif. Media sosial bisa menjadi tempat belajar, mencari hiburan, atau sekadar terhubung dengan orang lain. Masalah muncul ketika kita tidak lagi mengatur penggunaannya, tetapi justru mengikuti alurnya tanpa sadar. Dalam psikologi, ini disebut attentional capture, yaitu kondisi ketika lingkungan digital menarik perhatian kita dan mengarahkannya tanpa kita sadari.
Menurutku, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi merusak fokus, tetapi apakah kita masih punya kendali atas cara kita menggunakannya. Mengurangi dampaknya tidak berarti harus menjauhi teknologi. Kita bisa mulai dari langkah sederhana seperti memberi waktu tanpa ponsel, menyelesaikan bacaan sampai habis, atau berhenti sebentar sebelum membuka aplikasi.
Kebiasaan kecil seperti itu membuat kita bisa kembali mengatur fokus kita sendiri, bukan menyerahkannya pada algoritma yang menentukan apa yang harus kita lihat berikutnya.
Opini ini ditulis oleh Meilani Lestari Situngkir, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unmul 2025