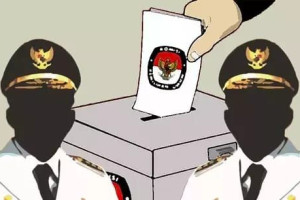Tanah, air dan udara, –merupakan sumber daya yang terbatas dan memiliki nilai yang sangat berharga– harus dikuasai negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun apa daya, di Indonesia frekuensi gelombang radio pun turut dieksploitasi oleh para tokoh politik yang mengalir darah ambisi untuk meningkatkan popularitasnya, baik itu dirinya sendiri maupun organisasi atau partai yang menaunginya.
Dikutip dari jatim.antaranews.com, ada 12 kanal media besar dengan pemilik yang beberapa memiliki atau menggeluti sebuah partai politik. Konsentrasi kepemilikan berdampak tak hanya pada keputusan redaksi lewat intervensi pemilik melalui "agenda setting", namun corak industri media juga mengakibatkan terjadinya uniformitas isi media karena prinsip pasar dan mengejar rating.
Terlihat dengan cara mereka dengan gencarnya me-manifestasikan konten-konten yang kurang mendidik seperti tayangan sinetron ataupun yang berbau kehidupan politiknya, padahal sesungguhnya masyarakat sana membutuhkan informasi yang setidaknya berfaedah tanpa adanya unsur politik.
Tentu kita sudah tidak asing dengan iklan-iklan politik di media besar tertentu, mereka berkampanye menyebarkan propaganda politik yang dikemas dalam bentuk lagu mars, demo perbaikan kesejahteraan masyarakat oleh partai politik tersebut, bahkan hanya sekedar ucapan perayaan hari-hari besar.
Lewat kemasan tersebut, secara kasat mata juga merubah pandangan masyarakat terhadap media-media yang menyebarkan propaganda tersebut. Misalnya, hampir seluruh masyarakat yang selalu melihat tayangan televisi hapal dengan nyanyian lagu mars partai A, bahkan hapal dengan nama pemilik partai tersebut.
Apa ini yang dinamakan informasi aktual? Apa ini yang disebut konten hiburan? Apa ini yang dijuluki media lahan popularitas? Berkaca dari pihak masyarakat yang tidak suka dengan konten politik ini, sudah tentu masyarakat berteriak agar unsur politik tadi dihapuskan, dan berhenti menggunakan media untuk kepentingan pribadi.
Sekedar info, di sebuah kegiatan saya pernah menonton sebuah film dokumenter yang berjudul “Di Balik Frekuensi” yang disutradarai oleh Ucu Agustin, yang mengisahkan bobroknya media sekarang. Dalam catatannya dalam film ini, Ucu Agustin menulis, “Pers dulu dibungkam, pers sekarang dibeli. Benarkah itu yang tengah terjadi di dunia media kita di era konglomerasi media pasca reformasi 14 tahun silam?”
Film ini mengisahkan kedua angle cerita berbeda, namun sama-sama menjelaskan mengenai “penjajahan saluran” yang terjadi di balik dua media berita terbesar di Indonesia, sebut saja media MT dan TO.
Cerita pertama diawali dari seorang jurnalis bernama Luviana, yang telah bekerja selama 10 tahun sebagai asisten produser berita untuk media MT. Namun pada tahun 2012, Luviana beserta beberapa temannya sesama jurnalis tidak diberi gaji selama beberapa bulan. Luviana merasakan ketidakadilan. Dia malah dipindahtugaskan dari bagian news ke HRD, bahkan sempat dilarang absen dan memasuki news room.
Luviana yang tidak mendapat kejelasan, lalu bersama teman-teman serikat pekerja dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mengadakan demo pada MT agar Luviana dapat bekerja kembali. Hingga film ini diputar perdana pada tahun 2013, kasus Luviana masih belum menemukan titik terang dan masih menunggu proses pengadilan.
Di cerita lain, ditayangkan pula perjuangan Hari Suwandi yang berjalan kaki dari Porong (Sidoarjo) ke Jakarta demi menuntut haknya dan warga korban lumpur Lapindo. Hari didampingi seorang temannya selama perjalanan, bahkan sempat menolak dan memarahi reporter TO.
Hal ini karena TO menyatakan bahwa Hari bukanlah warga Sidoarjo yang sengaja mencari sensasi. Namun, pihak TO dengan pintarnya mengubah alur cerita yang sudah disusun oleh Hari demi melindungi kepentingannya.
Secara mengejutkan, Hari datang bersama keluarganya di sebuah acara naungan TO, dan Hari meminta maaf kepada pihak TO dengan nada menyesal. Ending yang sangat memilukan bagi Hari, apalagi kalau bukan karena campur tangan pemilik TO yang sekaligus pengusaha PT Lapindo.
Setelah itu, Hari pun tidak kembali ke Sidoarjo dan jejaknya pun menguap begitu saja.
Sangat disayangkan ketika kita menyaksikan stasiun berita yang seharusnya memberikan informasi yang terpercaya, malah menyembunyikan kenyataan demi melindungi derajat mereka sendiri. Mereka tidak memerhatikan bagaimana masyarakat selalu dijejal konten-konten yang kurang memiliki makna, mengunci rapat-rapat kebenaran dari lapangan, demi mengunggulkan “produk” mereka.
Lalu, untuk siapa jurnalis bekerja? Untuk publik atau untuk pemilik media?
Tidak selamanya bekerja di media itu menyenangkan, tidak selamanya pekerjaan jurnalis itu keren. Dan tidak selamanya informasi yang disampaikan media 100% benar, walaupun “in media we trust,” tidak semuanya informasi itu sempurna. Diharapkan ini bisa dijadikan cerminan bagi masyarakat umum untuk menjadi lebih teliti dan cerdas dalam memilih informasi yang mereka terima. Selain itu, setidaknya ini menjadi gambaran bagaimana seharusnya media bekerja.
Ditulis oleh Mahmudhah Syarifatunnisa, mahasiswi Manajemen angkatan 2016, FEB, seusai mengikuti Journalistic Camp Sketsa 2017