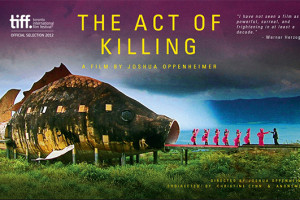Sumber Gambar: Pexels
Pagi ini, adikku berwarna merah. Ia tak jadi bersekolah, padahal mama sudah mengantarnya ke sekolah pagi-pagi buta, sebelum jam tujuh. Jam tujuh lewat sepuluh, ia pulang lagi sambil menggerutu. Katanya, telur gulungnya direbut temannya, sedangkan uang sakunya sudah habis pagi itu juga. Hari esok terlalu lama untuk menuntaskan keinginannya untuk makan telur gulung, sebab bisa jadi ia malah ingin makan kue leker atau bahkan gulali.
Mama mendengarkan ceritanya dengan seksama. Sambil menenangkan adikku, Mama dipenuhi warna biru. Mama seperti berada di lautan. Bedanya, mama tidak dihantam ombak. Akhirnya, mama memberi adik uang saku tambahan dan mengantarnya kembali ke sekolah. Di sana, mama menjadi merah muda, dan adikku menjadi biru, tetapi tidak sebiru warna Mama tadi. Biru adikku lebih kelam, tua, dan sedikit bercampur dengan kelabu.
Satu hal yang unik tentang mama, beliau memberi kami nama yang berhubungan dengan warna. Alhasil, aku lahir dengan nama Kapisa, sedangkan adikku bernama Dewangga. Sejak kecil, aku pikir semua yang kulihat ini adalah hal yang normal. Manusia selalu dikelilingi warna-warna yang berbeda dan selalu berganti setiap saat. Dulu, aku sering menunjuk orang-orang yang lalu-lalang di jalan sambil meneriakkan nama-nama warna. Mereka mungkin mengira bahwa aku sedang belajar menghafal, tapi kenyataannya aku berusaha memanggil mereka dengan warna yang kulihat di sekelilingnya.
“Kapisa, pulang kuliah nanti tolong mampir beli susu, ya? Kamu masih ada pegangan?” tanya mama sambil sibuk mencuci piring. Di antara suara piring-piring yang beradu, tiba-tiba warna jingga bercampur kuning muncul dari kepala mama. Biasanya, ini terjadi saat keuangan kami menipis. "Oh, ya, nilai UAS sudah keluar semua?"
Aku sengaja menciptakan jeda yang canggung sembari membuat suara-suara kertas dan buku untuk menghindari menjawab pertanyaan itu. "Susu full cream, kan?" tanyaku untuk memastikan setelah pura-pura sibuk sendiri. Setelah melihat anggukan mama, sudah dipastikan pulang kuliah nanti aku harus membelinya.
Menjadi seorang penglihat warna tak lantas membuatku jadi antisosial, meskipun terkadang mataku sakit karena melihat berbagai warna yang ngejreng. Kelebihan ini bisa membuatku memahami perasaan dan emosi orang lain dengan baik. Misalnya, hari ini mayoritas anak rantau di kelasku dikelilingi warna kelabu dan coklat, yang mungkin terjadi karena faktor akhir bulan.
Tapi, ada satu orang yang berbeda. Ia tampak sibuk mencatat di bangku paling depan sembari dikepung oleh warna-warna yang cerah dan mencolok, seperti warna merah, merah muda, hijau, biru, dan masih banyak lagi. Tanpa melihat warna pun, semua orang juga akan tahu kalau ia sedang dalam mode penuh ambisi. Kinantan, atau lebih sering disapa dengan Kinan, adalah definisi perempuan sempurna yang termanifestasi di dunia nyata. Walau kami harus menempuh beberapa semester lagi untuk lulus, ia sudah punya banyak keahlian dan pengalaman yang cukup untuk membuat HRD perusahaan start up terkesan. Plus, ia terlahir dan tumbuh dengan sendok emas di mulutnya, dibarengi dengan otak encer yang mendukungnya untuk berprestasi di bidang apapun yang ia geluti.
Sepulangnya dari kelas, aku tak lupa untuk mampir ke supermarket. Saat membuka pintu, mataku bertemu dengan seseorang yang familier. Itu Kinan. Ia tersenyum ramah sambil melambaikan tangannya, masih dengan warna-warni yang menyelimutinya.
"Eh, Kapisa? Beli apa?" tanyanya. Aku menjawabnya dengan menunjukkan sekarton susu full cream yang kupegang erat-erat. Ia tertawa kecil sambil menutup mulutnya, lalu lanjut mengajakku mengobrol. "Udah mau pulang? Kalau enggak buru-buru, aku mau curhat, nih. Aku lagi bimbang, mungkin saran dari kamu bisa membantuku," ujarnya. Aku membalas dengan anggukan. Sebenarnya, aku tak terlalu dekat dengannya. Menjadi teman sekelasnya tentu membuatku minder parah.
Jadi, kami memutuskan untuk duduk di kursi depan supermarket. Tanpa basa-basi, ia mulai berkeluh-kesah. "Jadi, kemarin aku lolos beasiswa kuliah magister di luar negeri. Aku diterima di dua universitas, tetapi aku bingung mau pilih yang mana," keluhnya. Setelah itu, ia mulai menjabarkan kedua universitas terkenal yang menerimanya beserta opini dan pengalaman pribadinya terkait negara tempat universitas tersebut berada.
Mendengarnya mengoceh dengan semangat, aku hanya bisa gigit jari. Kehidupan medioker ini memaksaku untuk menjadi manusia yang rasional dan realistis. Memang, aku familier dengan kampus yang ia sebutkan, tetapi aku tidak tahu-menahu tentang apapun yang ada di sana. Yang pasti, kampus-kampus itu sangat sempurna, mahal, dan tempat berkumpulnya orang-orang pintar.
"Jadi, menurutmu aku harus pilih yang mana, ya?" tanyanya dengan sedikit frustrasi. Aku masih melihat warna-warna yang mengelilinginya, namun kali ini warna oranye tiba-tiba menguap dari sela-sela rambutnya. Aku tahu betul apa yang sedang ia rasakan saat ini. Rasa iri mulai menggerogoti hatiku. Aku benci situasi seperti ini.
"Begini, aku heran, buat apa kamu bingung? Kalau aku ada di posisimu, memilih dengan mata tertutup pun akan kuterima hasilnya."
Ia tampak tidak puas dengan jawabanku. Warna merah, kuning sawo, dan ungu mendadak mencuat dari dadanya. "Memangnya, kamu yakin bisa menjalani hari-hari di sana? Maksudku, sainganmu orang-orang jenius, lho, bukan lagi teman-teman terpintar di kelas kita. Mungkin bakal susah dapat nilai bagus di sana. Bukannya meremehkanmu, tapi kamu paham saja, kan, kualitas pendidikan di sana itu seperti apa?"
Sekarang, dahinya mengkerut. Entah apa yang merasukiku, aku kembali membual. "Aku bahkan tidak mungkin seberuntung kamu. Ah, jadi ingat impian lama. Dulu aku pengen sekolah di Jepang. Lihat-lihat bunga sakura. Makan mochi juga."
Ia hanya menunduk lesu. Dari yang kudengar, ia adalah tipe orang yang terlalu memikirkan omongan orang tentang dirinya. Kini warna-warna cerah yang mengelilinginya perlahan memudar, berganti dengan warna-warna kelam dan pucat. Hitam legam, biru kelasi, abu-abu, dan cokelat gelap mulai bercampur aduk. Warnanya menjadi sangat jelek dan mengerikan. Perasaan tak nyaman yang kuat itu membuatku sadar akan perkataanku yang terlalu menyudutkannya.
"Maaf, Kapisa, aku jadi enggak enak sama kamu, mungkin—"
"Eh, Kinan, tapi dari ceritamu tadi, aku juga sependapat sama Bu Dosen yang mendukungmu ke universitas yang paling kamu sukai. Selamat, ya! Semangat menjalani kuliah di negeri orang!"
"Serius? Terima kasih banyak ya atas sarannya. Kamu juga semangat, ya! Kamu pasti bisa, yang penting tetap berusaha, sabar, dan berdoa, ya!"
Obrolan kami cukup sampai disitu. Sepanjang perjalanan pulang, wajahku dihiasi senyum getir. Setelah tertampar oleh jeleknya campuran warna pucat tadi, aku juga tiba-tiba merasa bersalah karena hampir menyalahgunakan anugerah ini kedalam hal yang tak baik. Yah, daripada terus-terusan membandingkan hidupku dengan Kinan, lebih baik aku melanjutkan kehidupanku yang biasa-biasa saja ini sampai titik di mana aku menemukan kebahagiaanku sendiri.
Cerpen ditulis oleh Andi Syifa Hanifaturrizkia, mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP 2022