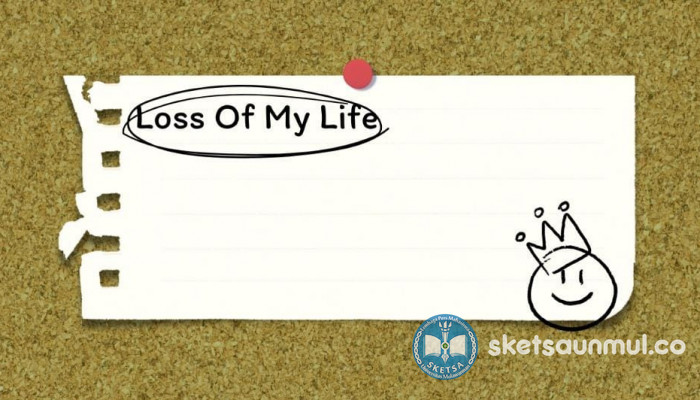
Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
Aku duduk di puncak gunung, mataku terpukau melihat keindahan gunung. Merasakan angin yang sepoi-sepoi berbisik di telingaku, seakan mengajakku untuk merenung.
Mengingatmu yang di masa lalu, yang sekarang telah menjadi orang asing bagiku. Mengingat bahwa kita pernah berada di puncak gunung bersama dengan canda dan tawa. Mengingat janji-janji yang telah kita lontarkan namun tak terlaksana.
Aku tahu bahwa takdir memisahkan kita. Kita berdua hanya sebatas kenangan yang perlahan akan segera memudar. Aku mengizinkan kenangan kita mengalir pergi. Namun, takdir tak selalu mudah untuk diterima.
Ada rasa bersalah yang menghantuiku. Tetapi aku juga sakit hati karena mengingat alasan mengapa kita berpisah. Padahal sebelum itu kamu pernah bilang kepadaku, “Aku serius sama kamu,” serius apa? Serius membuat luka baru?
Dahulu aku menerimamu walaupun kamu telah melakukan hal yang membuatku sangat kecewa. Aku memaafkanmu. Tetapi kamu mengulanginya lagi. Kamu membuat kesalahan yang membuatku kecewa lagi.
Tidak seperti dulu aku memikirkanmu dengan rasa senang dan berbunga-bunga. Sekarang aku memikirkanmu dengan perasaan yang biasa saja dan juga miris terhadap diriku yang bisa-bisanya pernah menerimamu lagi.
Aku memintamu untuk jujur. Aku hanya butuh kejujuran darimu. Sayangnya kamu memilih untuk berbohong. Aku merasa miris karena kamu berbohong kepadaku sampai bersumpah dengan membawa nama Tuhan. Sungguh kesalahan yang besar membawa-bawa nama Tuhan untuk berbohong.
Namun, ada saat di mana perasaan rindu padamu datang. Aku rindu dengan perlakuanmu yang membuatku tersenyum dan tertawa. Aku rindu di saat kita bermain game bersama. Aku benci di saat aku sudah disakiti tapi masih merindukan orang yang membuatku sakit hati. Aku benci karena telah berharap kepadamu. Aku berdoa pada Tuhan agar aku bisa melupakanmu.
Pada awalnya, aku malah semakin rindu padamu. Namun seiring berjalannya waktu, rasa rindu itu memudar.
“You don’t believe me even when i tell the truth,” kamu mengatakan itu dengan penuh emosi terhadapku. Biar aku beri tahu, kita sama-sama saling menyakiti satu sama lain. Aku tahu aku juga salah karena tidak mempercayaimu. Namun aku juga salah karena terlalu berharap kepadamu.
Tetapi aku tahu, aku harus menerima takdir. Aku harus menerima bahwa kamu pernah berkata, “kita harus terbiasa tanpa bersama”. Kalimat terakhir yang kamu lontarkan kepadaku sebelum kamu meninggalkan dan mengabaikanku.
Semenjak saat itu, aku mulai berusaha merubah diriku menjadi lebih baik, aku mengejar impianku seperti yang pernah aku ceritakan kepadamu. Aku semakin mendekatkan diriku kepada Tuhan. Dan sejujurnya, aku masih mendoakanmu agar kamu selalu diberikan yang terbaik dan diberi kebahagiaan.
Aku benar-benar harus menerima takdir, aku harus membiarkan diriku tumbuh dan berkembang. Aku harus percaya bahwa diluar sana ada yang akan mencintai kita seutuhnya. Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu. Mungkin takdir akan mempertemukan kita di tempat yang sebelumnya pernah kita datangi bersama. Sampai saat itu tiba, aku akan terus berusaha menjadi lebih baik dan melupakanmu dengan penuh keikhlasan.
Hari itu pun tiba, secara tidak sengaja dan tidak terduga kamu bertemu denganku.
Bertemu di puncak gunung yang sama seperti dulu kamu dan aku berada. Kamu dan aku saling berpapasan.
“Hai, Brianna,” sapamu terlebih dahulu.
Aku hanya membalas dengan senyuman. Bukan sombong, aku hanya tidak ingin kejadian yang membuatku merasakan sakit itu terulang kembali.
“Apa yang kamu lakukan disini?,” tanyamu kepadaku.
“Mencari ketenangan.”
“Sama, aku pun mencari ketenangan,” ujarmu sambil memasukkan tangan ke saku celana dan melihat pemandangan.
Suasananya begitu canggung, kita saling diam satu sama lain selama kurang lebih 10 menit.
“Maaf,” aku mulai membuka bahan obrolan dengan meminta maaf.
“Maaf untuk apa?”
“Maaf karena kita menjadi seperti ini”
“Untuk apa minta maaf? It’s not your fault. Kamu masih aja belum berubah, dari dulu selalu meminta maaf padahal kamu tidak salah.”
Mendengarnya mengucapkan kalimat itu, membuatku tersenyum miris.
“Aku minta maaf kepadamu,” ujarmu kepadaku.
“Ya, memang harus seperti itu, kamu yang minta maaf,” aku berbicara seperti itu karena mengingat bahwa kamu tidak meminta maaf saat dulu di mana kita masih menjalin hubungan.
Kamu hanya tertawa miris sambil mengarahkan pandanganmu ke aku,
“aku lega bisa minta maaf secara langsung kepadamu, sekarang aku pergi dulu ya,” kamu berbicara seperti itu sembari meninggalkanku sendirian.
Tidak masalah, memang seharusnya seperti itu. Sudah takdirnya seperti itu. Harus menerima takdir bahwa kita tidak bisa bersatu. Memangnya mau berharap apa? Kita memang pernah bahagia saat bersama, namun sekarang kita bahagia dengan jalan yang berbeda.
Cerpen ini ditulis oleh Lola Setia Hidayani, mahasiswi Fahutan Unmul 2023




