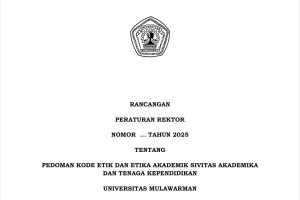Sumber Gambar : Mongabay
SKETSA – Greenpeace Indonesia mengunggah investigasi antara Greenpeace Internasional bersama Forensic Architecture pada 12 November lalu. Dalam situsnya, terungkaplah kegiatan Korindo, sebuah perusahaan perkebunan milik konglomerat Indonesia-Korea yang telah membakar lahan untuk kepentingan ekspansi perkebunan di Provinsi Papua. Hasil lain yang dikutip dari Forest Watch Indonesia (FWI), lebih dari 23 juta hektare atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Setidaknya, FWI mencatat Indonesia telah kehilangan hutan seluas itu sejak tahun 2000-2017.
Pada Selasa (17/11), Sketsa sempat meminta tanggapan akademisi Fakultas Kehutanan (Fahutan), Yaya Rayadin. Ia menuturkan, sebelum tahun 2000 pembukaan lahan dilakukan dengan pembakaran hutan sebab murah dan cepat. Tetapi, kegiatan ini mengganggu warga sekitar. Seperti munculnya polusi udara, keterbatasan jarak pandang, penerbangan terganggu hingga menyebabkan hewan-hewan yang masuk dalam kelompok herpetologi dan insek akan habis. Karena itu, pemerintah melarang ekspansi lahan dengan cara pembakaran hutan yang kemudian tertuang pada UU Lingkungan Hidup tahun 2009.
Dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak ada yang bisa disembunyikan. Sehingga seharusnya kebakaran hutan yang disengaja ataupun tidak dapat dengan mudah terdeteksi oleh sistem. Disinggung terkait ganti rugi yang kerap kali muncul mengikuti isu ini, ia menjelaskan bahwa konteks tersebut bukanlah ganti rugi namun bermaksud agar kegiatan perusahaan itu lancar.
"Ada yang namanya enviromental valuation. Satu hektare berapa nilai di dalamnya, berapa nilai tegakkan di dalamnya, berapa nilai resapan karbon di dalamnya, berapa nilai macam-macam sumber pakan di dalamnya, berapa nilai tanaman obat di dalamnya. Tidak bisa (ganti rugi) tidak masuk akal. Dalam konteks sawit, perusahaan juga diwajibkan membuat plasma. Jadi PT yang bersangkutan menyiapkan plasma tidak untuk masyarakat? Kalau tidak, wah berarti ini pengin untung sendiri," paparnya.
Dalam kaitannya dengan pemberitaan hutan Papua yang beredar, ia berharap pemerintah tidak hanya menunggu laporan. Komitmen perusahaan yang tertuang di dalam rencana pembangunan maupun Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) harus diawasi dengan benar, sebab tekanan pasar cukup besar. Pengawasan sangat diperlukan baik yang tertuang dalam dokumen Amdal maupun dokumen lainnya.
Dicky Wilyam Sari, mahasiswa Fakultas Kehutanan turut menyampaikan kekecewaannya terhadap isu ini. Menurutnya, hutan tersebut telah menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Papua untuk menopang kehidupan sehari-hari dan menjamin kesejahteraan hidup. Selain itu, ganti rugi yang dilakukan oleh PT Korindo sangat tidak sebanding.
Dicky menyebutkan, yang diperlukan Indonesia tidak hanya menghentikan deforestasi tetapi juga bagaimana agar para perusak hutan dapat bertanggung jawab. “Hal ini sejalan dengan polluter pays principle, dan mendorong negara agar lebih serius dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro perlindungan hutan dan restorasi dan penegakan hukum terhadap para perusahaan perusak hutan,” tegasnya, Minggu (15/11).
Sudut Pandang Hukum
Salah satu akademisi Hukum Unmul, Rahmawati Al Hidayah menerangkan beberapa hal kepada kami terkait regulasi hukum yang digunakan pada kasus-kasus serupa. Untuk kegiatan usaha perkebunan seperti kelapa sawit, bentuk-bentuk lain seperti hutan tanaman industri memang perlu membuka lahan. Secara hukum, sudah ada pengaturan baik dalam tingkat Undang-Undang maupun peraturan menteri hingga ke peraturan daerah.
Misalnya pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Di dalamnya diatur beberapa hal, salah satunya pada Bab X Bagian 3 Pasal 69 yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Regulasi lainnya ialah peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 pada pasal 4, menjelaskan masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan pembakaran luas lahan maksimum 2 hektare per kepala keluarga.
"Jadi, tidak sembarang bakar dan kemudian larangannya itu tidak boleh dilakukan di musim kemarau dan seterusnya. Kebolehan membuka lahan dengan cara dibakar itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat yang memiliki keilmuan khusus. Kemudian cara-cara mekanisme tertentu ketika mereka membuka lahan dengan cara dibakar," paparnya kala membandingkan regulasi yang ditujukan untuk perusahaan dan masyarakat hukum adat, Rabu (2/12).
Menurut Rahmawati, terdapat kelemahan dari sisi penegakan hukum sebab Indonesia masih mengandalkan investasi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Ketika berbenturan antara kepentingan lingkungan dengan investasi, hasilnya cenderung mengedepankan kepentingan investasi. Contoh paling nyata, lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Kebutuhan investasi lebih diutamakan, padahal ada hal lain yang dikorbankan seperti keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Karena tadi saya bisa katakan penegakan hukum yang lemah. Paling buruh yang disuruh bakar saja atau orang yang kedapatan membakar, sementara perusahaan atau pemilik perusahaan itu lepas dari hukuman. Ada yang dihukum, (tapi) hukumannya itu tadi susah untuk dieksekusi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kejadian yang melibatkan Korindo pernah terjadi di 2016, dan sempat menolak moratorium. Dari kejadian tersebut, ia berpesan agar setiap individu selalu peduli terhadap isu lingkungan dan berpartisipasi lewat kegiatan sederhana.
Terlebih baginya, dalam perspektif Islam telah diingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh ulah manusia. Rahmawati berpesan agar ini menjadi pengingat untuk mengawasi berbagai keputusan yang diambil pemerintah. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata menimbulkan kerusakan bagi lingkungan kita. (yen/kus/rst/fzn)