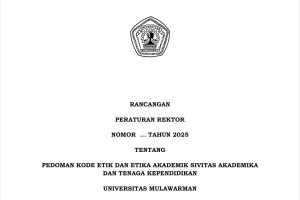Dilema Politik Dinasti di Indonesia
politik dinasti yang terjadi di Indonesia.

Sumber Gambar : Kompas
SKETSA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah usai digelar serempak di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2020 lalu. Miris, pesta demokrasi daerah ini dilaksanakan saat angka kematian atas pandemi Covid-19 berada pada puncaknya. Dilansir dari m.cnnidonesia.com, angka kematian tercatat berada di angka 18.171. Adapun akumulasi kasus positif Covid-19 mencapai 592.900 kasus.
Tak hanya digelar saat pandemi berlangsung, terdapat pula hal menarik yang patut jadi sorotan. Seperti bagaimana anak dan menantu presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution ikut berlaga dalam Pilkada kali ini. Mereka sama-sama mencalonkan diri sebagai wali kota. Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan Bobby sebagai wali kota Medan. Keduanya pun menang pada gelaran ini berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) Charta Politika.
Kejadian yang disebut sebagai 'sejarah' ini mengingatkan kita kembali dengan politik dinasti yang sering kali terjadi di Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik dinasti merupakan suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat yang berkuasa.
Secara etis, praktik ini memang tidak baik. Namun secara yudiris, selama mereka memenuhi persyaratan (ketika mencalonkan diri) mereka memiliki hak untuk terjun dalam kontes politik.
Memang, tak ada larangan atau batasan bagi siapa pun untuk berpartisipasi dalam pemilihan semacam ini. Apalagi, sistem yang digunakan di Indonesia membuat seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memilih sendiri pemimpin yang diinginkan. Lalu, bagaimana praktik ini terlihat dari pandangan civitas academica Unmul?
Sempat diwawancarai Sketsa pada Minggu (17/12/20) lalu, Budiman selaku dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan menyebutkan jika fenomena ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang dampak positif.
"Hal itu (dampak negatif) dapat kita lihat dari potensi-potensi korupsi, kolusi dan nepotisme," tuturnya.
Ia mengatakan, politik dinasti membuat kesempatan bersaing dalam politik menjadi lebih sempit. "Kebanyakan (para calon) yang keder duluan jika harus bersaing dengan istrinya bupati atau anaknya bupati. Mereka beranggapan 'ngapain?'" kata Budiman.
Faktor lain penyebab adanya politik dinasti adalah kecenderungan partai politik yang jarang menggunakan kader mereka untuk maju dalam sebuah pemilu dan lebih mengutamakan keluarga. Baginya, hal ini memberikan dampak demokrasi yang tidak sehat. Sebab tidak memberikan kesempatan untuk pihak lain dalam bersaing secara demokrasi.
"Para pemilih (seharusnya) dapat lebih selektif dan melihat rekam jejak para calon pemimpin, agar fenomena ini tidak terus terulang," tukasnya.
Di sisi lain, Alfian salah satu dosen Hukum Tata Negara berpendapat bahwa politik dinasti dapat dilakukan. Asal dalam prosesnya tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyalahi undang-undang.
Baginya, tak masalah selama calonnya memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas. Apalagi jika cara yang ditempuh calon tersebut sah secara konstitusional dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Toh, sampai saat ini tidak ada aturan yang mengebiri hak politik seseorang untuk maju menjadi calon kepala daerah atau apa pun itu. Artinya, semua warga negara dapat mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah," jelasnya kepada Sketsa, Senin (21/12/20).
Alfian juga menuturkan, istilah politik dinasti kurang tepat untuk diberikan terhadap fenomena ini. Menurutnya, keadaan ini disebut dengan oligarki. Karena, para kerabat pemimpin daerah tersebut tetap harus bersaing dan menjalankan proses pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Berbeda dengan konsep dinasti pada bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki, di mana jabatan raja langsung diturunkan kepada putra mahkota kerajaan," ujar Alfian.
Untuknya, ini sangat subjektif sebab tergantung oknum dan individu masing-masing. "Bahwa kenapa dia ingin menjadi seorang pemimpin atau presiden atau wali kota dan lainnya. Kalau dia niatnya menjadi seorang pemimpin (yang) benar-benar ingin menyejahterakan rakyatnya, tidak masalah dan tentu saja itu sangat mulia."
"Tetapi, apabila ada oknum (yang) ingin menjadi seorang pemimpin karena niat untuk mengeksploitasi sumber daya manusia atau sumber daya alam, nepotisme, korupsi, kolusi dan lain-lain. Maka oknum inilah (yang) biasanya sangat haus akan kekuasaan dan biasanya tidak rela apabila tampuk kepemimpinannya jatuh ke tangan orang lain," tutupnya. (sii/zar/eng/len)