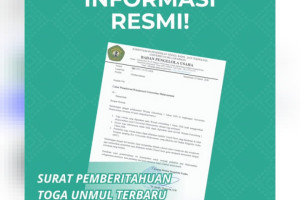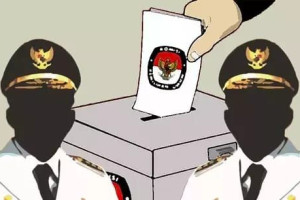Sumber foto: Kompas.com
Jika pernah menonton Charlie and the Chocolate Factory atau setidaknya pernah mendengar kisahnya pasti kenal dengan Charlie Bucket. Ia seorang bocah dari keluarga kelas bawah yang tinggal di rumah reyot dekat pabrik coklat milik Willy Wonka, bersama kedua orang tua dan empat kakek-neneknya yang masih hidup. Charlie yang bagaikan kejatuhan durian runtuh mendapatkan golden ticket dari sebungkus cokelat, berkesempatan menyambangi dan berkelana di dalam pabrik coklatnya Willy Wonka. Tidak hanya Charlie saja, setidaknya ada empat anak lain yang juga dapat golden ticket. Cukup sampai disitu penjelasannya, karena selebihnya kita sudah tahu kelanjutannya dan resensinya bisa dicari dengan mudah lewat internet.
Lalu, apa hubungannya Charlie and the Chocolate Factory dengan judul maupun yang selanjutnya akan ada dalam tulisan ini? Mungkin hampir tidak ada, namun izinkan saya mengajak pembaca sekalian untuk menyorot sejenak keluarga kecil Charlie. Ibu dan ayahnya siang-malam membanting tulang tidak hanya untuk menghidupi Charlie saja, namun juga orang tua mereka yang sudah tua renta. Maksud saya adalah, keluarga Charlie dalam film tersebut semacam gambaran mengenai ketimpangan demografis. Contoh nyatanya adalah negara Jepang di mana populasi lansianya lebih dari 30 persen dari total jumlah penduduk. Mengenaskan? Bisa jadi, karena dampaknya cukup signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi sosial dalam jangka panjang. Lalu konteksnya dengan yang ada di Indonesia?
Boleh jadi demografi kita masih dalam batasan “wajar”. Gaung bonus demografi di tahun 2020 yang sering disuarakan jadi semacam secercah harapan bagi bangsa ini. Angkatan kerja yang melimpah jumlahnya ini dan relatif muda secara usia digadang-gadang mampu memakmurkan perekonomian Indonesia kira-kira selama 10-15 tahun. Akan tetapi, pernahkah terlintas dalam benak kita jika generasi milenial dan generasi Z mampu mengejar kesempatan tersebut sebelum mereka sendiri akhirnya juga menua? Jelas kita sepatutnya khawatir jika melewatkan kesempatan tersebut, karena menua adalah hal yang niscaya.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sendiri saat ini sebesar 1,49 persen. Melihat proyeksi penduduk lansia 2010 – 2035 dari Kementerian Kesehatan, tahun 2035 jumlah penduduk lansia diperkirakan sebanyak 48,2 juta jiwa (15,77%). Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi pada 2045 menjadi 63,3 juta jiwa (19,9%).
Jelas kita harus optimis menyongsong bonus demografi yang akan datang. Namun membayangkan skenario Indonesia menua dahulu sebelum kaya raya, rasanya kita harus sedikit was-was. Selain itu, carut-marut dan problematika yang dihadapi negeri ini nyatanya membuat sebagian dari kita sebagai pemuda Indonesia resah. Apa yang bisa diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen jika kesempatan untuk menjadi tenaga kerja sendiri susah didapat.
Terkadang kita dihibur dengan kata-kata penyemangat bahwa semua yang diinginkan bisa terwujud jika ada niat. Yang perlu diingat adalah tidak semua milenial bernasib seperti Nadiem Makarim dengan kesuksesan startup-nya, apalagi Mark Zuckeberg. Jauh sekali perbandingannya. Tapi siapalah saya, mungkin orang yang lebih kompeten di bidang terkait berkata lain. Mungkin kedengarannya sinis, tapi saya tidak bermaksud demikian. Terkadang kita mengabaikan latar belakang dan wealth dari keluarga seorang individu berperan dalam menentukan derajat kesuksesan hidupnya
Seringkali kita menyalahkan sistem pendidikan yang kurang memadai dan belum merata sebagai penyebab mengapa predikat negara maju belum kita raih. Memang sistem pendidikan berperan dalam menentukan nasib generasi penerus dan arah pembangunan suatu negara, namun kesenjangan ekonomi dan sosial juga patut untuk dibenahi.
Lalu bagaimana pemuda generasi milenial dan generasi Z menghadapi tantangan tersebut? Macam-macam. Ada yang turun ke jalan meneriakkan slogan-slogan perjuangan sembari mempertanyakan argumentasi dari narasi yang disampaikan penguasa. Ada yang memilih masuk ke dalam lingkar kekuasaan supaya bisa menelurkan kebijakan yang progresif dan pro-rakyat. Tidak jarang juga ada yang oblivious (secara sadar maupun tidak) dengan sekitarnya dan lebih memikirkan bagaimana mereka bisa menggemukkan pundi-pundi finansial dan hasrat konsumtifnya.
Terkadang antara yang turun ke jalan dan yang masuk ke lingkar kekuasaan menganggap merekalah yang paling benar. Yang turun ke jalan menganggap oposisi adalah gerakan yang murni dan akan terus ada selama pemerintah terus berkuasa, serta menganggap orang yang masuk ke dalam lingkar kekuasaan sebagai pengkhianat perjuangan karena telah terkooptasi oleh kekuasaan itu sendiri. Di sisi lain, yang memilih masuk ke dalam lingkar kekuasaan menganggap dirinya realistis dan menganggap kaum yang turun ke jalan termakan romantisasi pergerakan pendahulunya.
Berbicara mengenai gerakan progresif, mungkin ada banyak yang lebih paham dari saya mengenai sejarah serta eksistensi dan orientasi pergerakan di luar sana. Perbedaan pandangan antara golongan tersebut sebenarnya wajar-wajar saja dalam arus dialektika, namun akan jadi penghalang jika perbedaan tersebut mengakibatkan konflik dan melenceng dari tujuan sebenarnya, yaitu gerakan yang membangun kesadaran dan didasari atas kepentingan rakyat.
Di sisi lain masih terlihat jelas dalam beberapa pergerakan kita terkadang masih belum bisa membangun dan menyamakan persepsi dalam perjuangan secara total, apalagi konsolidasi secara menyeluruh. Terlebih dalam hal yang tidak hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga kaum buruh, petani, dan kelompok marginal lainnya. Seolah-olah kelompok tersebut berenang di kolamnya masing-masing dalam memperjuangkan suara dan aspirasinya.
Entah harus menunggu perayaan Sumpah Pemuda yang keberapa lagi agar generasi kekinian bisa sadar dengan substansi tiga poin yang disampaikan di Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928. Pemuda kita dalam beberapa hal sepandangan perihal mengapa-nya, namun tidak sejalan tentang bagaimana-nya.
Ditulis oleh Putera Tiya Ilahi, mahasiswa Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya 2015.