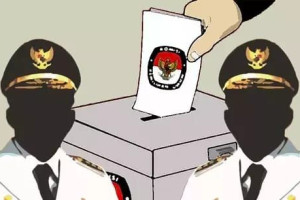Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
Kebudayaan adalah hal yang terus bergerak mengikuti pergerakan zaman. Olehnya, kebudayaan bersifat dinamis. Perubahan yang dinamis melahirkan dinamika tak berkesudahan dari siklus hidup sebuah kebudayaan.
Perubahan budaya dan percampuran budaya adalah keniscayaan yang mesti dilihat secara terbuka dan responsif. Perubahan budaya dengan berbagai skenario dan eksistensinya tak dapat mengelakkan terjadinya perjumpaan dan percampuran budaya. Identitas yang hibrid dan beragam semakin sulit dihindari.
Mestinya, hal di atas mewarnai pembicaraan pada dialog publik yang dihelat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Unmul, pada 6 November 2021 lalu. Dialog publik tersebut mengangkat tema “Modernitas dan Identitas: Membincang Kesiapan IKN Baru dalam Perspektif Lintas Budaya Nusantara”.
Bagaimana menghadapi perjumpaan kebudayaan yang tidak bisa dihindari adalah pertanyaan kunci yang mesti dijawab. Ketahanan budaya dan pelestarian budaya adalah kosa kata lazim yang mengemuka di percakapan tersebut. Sayangnya, kosa kata ketahanan dan pelestarian budaya ini adalah kosakata yang lahir dari cara pandang esensialis memandang kebudayaan dan berpretensi menatap kebudayaan sebagai sesuatu yang statis, tak bergerak mengikuti siklus hidup zamannya.
Dalam diskusi tersebut, dihadirkan pembicara satu orang dari kalangan akademisi Unmul, dan tiga di antaranya dari lembaga adat, seniman, dan budayawan dari luar Unmul. Hal yang kurang bunyi pada dialog itu adalah bagaimana strategi kebudayaan, kebijakan budaya, dan siasat kebudayaan menghadapi perubahan kebudayaan ke depan dengan hadirnya IKN baru di Kaltim sebagai keniscayaan tak terhindarkan. Karena perubahan adalah keniscayaan, maka cara menghadapi perubahan akibat perjumpaan itulah yang mestinya digeledah lebih luas dan mendalam. Bertahan dan berharap lestari bukan saja merupakan cara pandang lama, tapi tidak cukup.
Ketiga pokok bahasan di atas (strategi, kebijakan, dan siasat kebudayaan) sesungguhnya lebih mengarah ke perspektif cultural studies ketimbang study of culture (antropologis-sosiologis) yang lebih bicara ke ketahanan budaya dan pelestarian budaya. Kondisi terdominasi-terhegemoni, bernegosiasi dan bercampur, serta resistensi adalah tiga kondisi yang lazim mengemuka ketika kita bicara dinamika kebudayaan dari perspektif cultural studies (kajian budaya).
Dalam ketiga kemungkinan skenario tersebut, di manakah posisi identitas lokal di Kaltim menghadapi perjumpaan budaya yang diprediksi akan deras bin masif tersebut?
Prediksi dan ramalan-ramalan (forecast) membaca ketiga skenario itulah yang mesti dielaborasi dan dibaca lebih jauh. Di mana posisi Kaltim ke depan? Bagaimana perubahan yang bakal terjadi? Apa yang mesti dilakukan? Strategi, kebijakan, dan siasat apa yang dibutuhkan? Sudah sejauh mana pemerintah dan masyarakat sipil Kaltim bersiap diri? Apa yang mesti disiapkan dari sekarang, dan ke depannya? Sampai seterusnya.
Masih banyak lagi pertanyaan yang bisa dielaborasi dan dikemukakan secara akademis dan kritis memandang potensi perubahan budaya di calon Ibukota Negara (IKN) baru tersebut, jika pun nantinya benar-benar terwujud.
Hal yang perlu dibaca juga adalah “pasifikasi” budaya di arus bawah. Bagaimana kebudayaan masyarakat lokal mencoba dipasifkan dengan ragam praktiknya. Bagaimana pula kebudayaan lokal yang sebelumnya kurang diapresiasi justru belakangan dikomodifikasi melalui industri budaya. Industri pariwisata dan maraknya festival budaya adalah dua di antara sekian potensi komodifikasi budaya lokal ini. Cara pandang kritis bisa membawa kita lebih jauh mengelaborasi perihal ini. Beberapa studi juga telah mengangkatnya (Lihat Maunati, 2004 dan Aziz, 2014).
Diskursus di atas mestinya menjadi semacam prolog diskusi. Di mana diskursus tersebut akan dikontekstuliasasi oleh para pembicara dari luar kampus dan dikonseptualisasi oleh akademisi dari kampus, dalam hal ini Unmul.
Cara pandang study of culture yang relatif positivis konstruktivis secara akademis, sepertinya mewarnai secara dominan cara pandang di diskusi ini. Minus cara pandang cultural studies (kajian budaya) yang berperspektif kritis dan emansipatoris. Sehingga kekayaan perspektif kurang mengemuka dalam menganalisis dan mengevaluasi ragam masalah yang datang dari luar sana.
LP2M mestinya mengarahkan topik diskusinya ke topik yang lebih komprehensif dengan mengakomodir keragaman cara pandang menilai kebudayaan. Dengan begitu, setidaknya pihak kampus mendapatkan banyak gambaran (inventarisasi masalah) dari luar, sekaligus yang dari luar kampus mendapatkan konsep keilmuan dan perspektif dari para akademisi atau ilmuwan di kampus yang lebih kaya. Intinya, pihak luar menyiapkan konteks, pihak dalam kampus menyiapkan konsep. Idealnya, konseptualisasi dan kontekstualisasi melalui pertukaran informasi dan gagasan mestinya menjadi roh dari dialog publik seperti ini.
Dengan begitu, akan ada hal yang dijadikan bahan kajian atau rekomendasi hasil kajian untuk pengambil kebijakan. Selain itu, dapat pula menjadi bahan riset dan publikasi baru bagi LP2M mengenai bagaimana dinamika budaya di lingkungan hutan tropis calon IKN baru. Publik pun dapat memahami apa yang sedang dan bakal terjadi sesungguhnya. Baik secara konseptual, terlebih secara kontekstual di lapangan.
Sudah lazim kiranya kalau aktivis-seniman-budayawan akan banyak bicara mengenai pengalaman dan fakta-fakta di lapangan. Hal demikian menjadi asupan bergizi bagi para akademisi dan intelektual di universitas. Tugas kampus dengan ilmuwan dan akademisinyalah yang mengonseptualisasi dan memberikan perspektif keilmuan sekaligus menetralisir anasir-anasir pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Demikianlah saling asah dan asuh antara kampus dan masyarakat sekitarnya menghasilkan kontribusi yang produktif.
Sekiranya, komposisi pembicara yang kebanyakan dari luar kampus, perspektif keilmuan akan sedikit sulit dielaborasi. Diskusi akan lebih banyak mendengar curahan pengalaman para pelaku dari lapangan. Rentetan permasalahan akan tersaji, karena domain teman-teman di lapangan memang demikian. Hal yang dibutuhkan sebetulnya adalah keseimbangan informasi dan pengalaman lapangan dengan cara baca keilmuan untuk mengabstraksi, mengkonseptualisasi, dan mengevaluasi peristiwa dan pengetahuan yang ada.
Dengan demikian, pembicara dari kalangan akademisi semestinya lebih dari satu, dengan perspektif yang sebaiknya juga beragam sebagaimana beragamnya pembicara dari luar kampus yang menghadirkan kalangan lembaga adat, seniman, budayawan dan penulis.
Artinya, satu akademisi dengan perspektif budaya positivis-konstruktivis (antropologi-sosiologi budaya), satunya lagi dari perspektif kritis, yakni kajian budaya (cultural studies) dapat memperkaya pembahasan tema yang memang lagi hangat ini. Dengan begitu, publik dapat memperoleh cara pandang yang lebih kaya, lagi mencerahkan.
Terakhir, membicarakan kebudayaan dari kacamata modernitas dan identitas memang tak ada habisnya. Selagi manusia masih bergerak, saat itu pula perjumpaan dan perubahan kebudayaan terjadi. Kita tidak saja dituntut untuk bersiap, namun mesti menyambutnya dengan sigap. Karena sudah menjadi hukum semesta kebudayaan jugalah, bahwa yang tidak siap dan kurang sigaplah yang akan duluan punah.
Unmul dan Kaltim tentu tak ingin menjadi yang punah duluan, bukan?
*Tulisan ini adalah catatan reflektif dari dialog publik oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman dengan tema “Antara Modernitas dan Identitas: Membincang Kesiapan IKN Baru dalam Perspektif Lintas Budaya Nusantara”.
**Tulisan ini juga dibuat berdasarkan laporan kaltimkece.id bertajuk "Dari Diskusi di Unmul, Menjawab Kekhawatiran Tergerusnya Identitas Lokal oleh Modernitas IKN", 8 November 2021.
Opini ditulis oleh Nasrullah, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unmul.