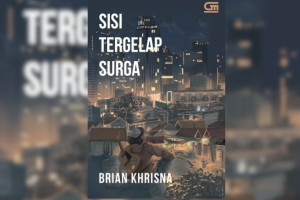Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
Suatu hari, saya menemukan sebuah karya yang menarik perhatian saya—bermula dari cerpen "Pembeliant" dan berkembang menjadi novel epik "Panglima dan Muslihat Koloni" karya A. F. Sandro. Minat saya untuk membaca karya ini tumbuh, tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap sastra lokal, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi sastra di Kalimantan Timur yang kian kehilangan gairah.
Dalam konteks ini, novel ini menawarkan penyegaran yang sangat dibutuhkan. Tulisan ini akan mengulas secara mendalam keunggulan, tantangan struktural, dan potensi pengembangannya di masa depan, dengan pendekatan kritis yang konstruktif dan bersifat reflektif.
Karya ini lahir dari sebuah transformasi naratif yang menarik; bermula dari cerpen sederhana “Pembeliant”, kemudian berevolusi menjadi sebuah novel besar yang mengusung tema perlawanan masyarakat Dayak terhadap penjajahan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Proses transisi ini tidak hanya memperluas cakrawala naratif, melainkan juga menantang penulis untuk mempertahankan esensi cerita yang intim sembari mengembangkannya ke dalam bentuk yang lebih kompleks dan epik.
Novel ini menampilkan tokoh utama, Nanjan, bersama dengan Nara dan Taman, yang bersama-sama menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan dilema moral dalam menghadapi kekejaman kolonial. Di sisi lain, ‘Pembeliant’ menawarkan kisah personal yang lebih intim, terutama mengenai hubungan ayah-anak melalui tokoh Sanja, serta pencarian mistis terhadap Pusaka Pembeliant yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan.
Novel ini mengisahkan perjuangan Nanjan, seorang pemuda yang mewarisi kekuatan legendaris sebagai Panglima, dalam menghadapi kekejaman penjajahan VOC. Bersama Nara dan Taman, ia menjalani perjalanan epik yang dipenuhi konflik moral, dilema kekuasaan, dan pencarian jati diri.
Di balik pertarungan fisik yang mendebarkan, terdapat pertanyaan mendalam mengenai apakah kekuatan yang diwariskan merupakan berkah atau kutukan. Konflik ini diwarnai dengan intrik politik, peperangan epik, dan simbolisme yang kental, seperti penggunaan motif “ayam jago” sebagai metafora kepemimpinan.
Kumpulan cerpen “Pembeliant” terdiri atas lima bagian yang saling terhubung, menggambarkan dinamika hubungan antar generasi melalui perspektif yang lebih personal. Cerpen ini menyoroti hubungan emosional antara ayah dan anak melalui tokoh Sanja, sekaligus mengangkat unsur mistis dengan pencarian Pusaka Pembeliant. Dengan gaya yang lebih intim dan narasi yang padat, cerpen ini menyuguhkan kontras yang menarik antara keintiman hubungan personal dan kekuatan supranatural yang mewarnai dunia yang lebih luas dalam novel.
Salah satu kekuatan utama karya ini adalah kemampuannya menyatukan adegan aksi yang mendebarkan dengan momen refleksi yang mendalam. Misalnya, dalam adegan pertempuran antara Nanjan dan Timang, narasi dengan cepat beralih dari ketegangan fisik ke monolog internal Nanjan. Walaupun hal ini berhasil menambah dimensi psikologis dan memperlihatkan keraguan serta kegetiran karakter, transisi tersebut terkadang terasa agak mendadak.
Untuk mengoptimalkan dampak emosional, disarankan untuk menyisipkan deskripsi kondisi fisik—seperti napas tersengal, denyut jantung yang semakin kencang, atau sensasi rasa sakit yang menggetarkan—sebelum memasuki monolog internal. Teknik bridging semacam ini akan menciptakan transisi yang lebih halus antara aksi dan refleksi, sehingga pembaca dapat merasakan kegetiran momen tersebut secara lebih utuh tanpa mengganggu alur ketegangan.
Karakter-karakter utama seperti Nanjan, Nara, dan Taman ditampilkan dengan kompleksitas yang memukau. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penggerak plot, tetapi juga sebagai cermin yang memantulkan berbagai aspek nilai, konflik internal, dan identitas budaya. Sementara itu, Timang—yang diciptakan sebagai antagonis—berhasil tampil sebagai sosok yang lebih dari sekadar kekuatan fisik; ia adalah "force of nature" yang selalu selangkah lebih maju meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih pasca-penjara.
Saya menyarankan untuk mempertahankan penggunaan simbolisme, misalnya motif “ayam jago”, dan mengintegrasikannya kembali di momen-momen krusial dalam cerita. Walaupun penulis sengaja mengurangi konflik batin dalam karakter Timang untuk menjaga wibawanya, sedikit hint yang halus mengenai dimensi strategisnya—misalnya melalui dialog atau interaksi singkat—bisa menambah kedalaman tanpa mengurangi karismanya. Hal ini akan membuat karakter Timang menjadi lebih menakutkan dan tak terlupakan tanpa menimbulkan simpati yang berlebihan.
Transisi dari “Pembeliant” ke “Panglima dan Muslihat Koloni” merupakan elemen penting yang menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun terdapat usaha untuk mempertahankan tone intim dari versi cerpen, beberapa segmen terasa agak stretched dan kurang terintegrasi secara mulus.
Untuk meningkatkan kesinambungan naratif, disarankan untuk menyisipkan sub-bab pendek yang mengulas proses kreatif dan transformasi tersebut secara eksplisit. Misalnya, sebuah bagian meta-commentary yang menyoroti elemen-elemen yang dipertahankan (seperti nuansa personal dan emosional) serta yang diperluas (seperti skala konflik dan kompleksitas politik).
Pendekatan ini tidak hanya akan menambah kekayaan naratif, tetapi juga membantu pembaca mengapresiasi perjalanan evolusi karya dari bentuk cerpen yang sederhana hingga menjadi novel epik.
Berdasarkan analisis keseluruhan, berikut adalah beberapa masukan untuk pengembangan lanjutan:
Transisi Emosional: Perhalus jembatan antara adegan aksi dan momen refleksi. Sisipkan deskripsi kondisi fisik dan simbolik yang menguatkan pergeseran emosi, agar tiap adegan dapat menyampaikan beberapa tujuan sekaligus—emosional, mendebarkan, dan pengembangan karakter.
Pengembangan Karakter Antagonis: Meskipun Timang sengaja dibuat tanpa konflik batin mendalam untuk menghindari simpati, penambahan elemen strategis yang lebih halus—misalnya, dialog pendek yang menggambarkan kecerdasannya atau momen di mana ia secara singkat menampilkan sisi manipulatifnya—akan semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan yang selalu berada di depan.
Penyatuan Tema: Perkuat kesinambungan tema antara cerpen dan novel dengan menyoroti elemen personal yang tetap terjaga. Misalnya, momen-momen intim dalam ‘Pembeliant’ dapat diintegrasikan ke dalam novel dengan memasukkan kilas balik atau narasi introspektif yang mengaitkan pengalaman karakter secara lebih mendalam.
Secara keseluruhan, “Panglima dan Muslihat Koloni” serta “Pembeliant” merupakan karya yang kaya akan nilai sejarah, mitologi, dan dinamika interpersonal yang mendalam. Karya ini tidak hanya menawarkan narasi perlawanan heroik terhadap penjajahan, tetapi juga menggali aspek psikologis dan simbolis yang kompleks dalam diri para karakternya.
Meskipun terdapat beberapa aspek—seperti transisi antara aksi dan refleksi, dan pengembangan detail pada karakter antagonis—yang masih memiliki ruang untuk penyempurnaan, saya sangat mengapresiasi upaya penulis dalam menciptakan dunia yang sarat makna dan intrik.
Karya ini merupakan penyegaran bagi dunia sastra Kalimantan Timur dan membuktikan bahwa kreativitas serta keberanian dalam mengeksplorasi bentuk dan isi dapat menghasilkan narasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenung tentang nilai-nilai kepemimpinan, warisan budaya, dan pengorbanan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan karya ini kepada pembaca yang mengapresiasi literatur yang penuh dengan nuansa sejarah, fantasi, dan konflik batin yang mendalam.
Secara personal, saya merasa terinspirasi oleh karya ini, terutama karena Sandro berhasil menggabungkan elemen-elemen kecil yang memiliki makna simbolis mendalam dengan alur cerita yang epik. Saya yakin dengan beberapa penyempurnaan pada transisi emosional dan pengembangan karakter, karya ini akan semakin kuat dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan di benak pembacanya.
Opini ini ditulis Davynalia Pratiwi Putri, mahasiswi Sastra Indonesia FIB Unmul 2021