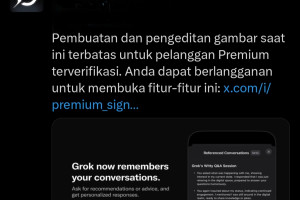Sumber Gambar: Project Multatuli
Pemerintah kembali mengesahkan regulasi yang menuai kritik di masyarakat, lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba). Secara normatif, regulasi ini membuka akses izin tambang tidak hanya bagi korporasi besar saja, tetapi juga koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diberikan prioritas untuk memperoleh wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan luasan tertentu hingga 2.500 hektare. Hal ini diperkuat lewat Pasal 26 C–26 F yang mengatur lebih jauh mengenai mekanisme verifikasi kriteria administratif oleh Menteri sebelum izin diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Sebelum koperasi dan UMKM, pemerintah telah lebih dulu membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan melalui PP 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021. Bahkan, perguruan tinggi juga sempat digadang-gadang untuk mengelola tambang melalui revisi kebijakan Minerba namun batal.
Dengan kata lain, regulasi ini secara formal membuka pintu lebar bagi badan usaha selain korporasi untuk masuk ke sektor tambang, sesuatu yang sebelumnya lebih didominasi korporasi besar. Dalihnya sederhana, demi pemerataan ekonomi rakyat dan memperluas pemanfaatan sumber daya alam. Namun, timbul pertanyaan mendasar, rakyat mana yang sebenarnya diuntungkan?
Di atas kertas, kebijakan ini tampak mulia. Koperasi diberi ruang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), seolah tambang kini bisa menjadi milik bersama. Tetapi realitas di lapangan jauh lebih krusial. Koperasi yang seharusnya jadi alat kesejahteraan rakyat, justru bisa jadi tameng baru bagi oligarki tambang. Alih-alih menyejahterakan rakyat, kebijakan ini berpotensi memperluas kerusakan lingkungan dengan legitimasi baru.
Koperasi memang diakui sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga secara formal dapat menjadi pemegang izin tambang. Namun, tujuan koperasi sejatinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mengelola tambang.
Sementara itu, UMKM hanyalah kategori usaha yang baru bisa memegang izin jika berbadan hukum yang pada dasarnya tidak dirancang untuk mengelola sektor ekstraktif.
Dikutip dari data buku Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batu bara 2021–2025 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dengan sumber daya permukaannya mencapai 36,9 miliar ton. Lokasi tambangnya tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), dan Berau.
Oleh karena itu, Kaltim telah menjadi saksi nyata bagaimana tambang meninggalkan jejak luka ekologis. Dikutip dari Editorial Kaltim, Komisi XII DPR RI menyoroti fakta bahwa lubang-lubang tambang itu tersebar di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Hingga 2024, tercatat masih ada lebih dari 2.700 lubang bekas tambang yang belum direklamasi.
Media Kaltim juga menyebutkan bahwa seluas 37.234 hektare lahan tambang di Kutim belum dijamin reklamasi (Jamrek) oleh perusahaan pemegang izin. Angka ini menjadikan Kutim sebagai penyumbang terbesar tunggakan Jamrek di Kaltim.
Lubang-lubang tambang yang menganga itu bukan hanya merusak lanskap, tetapi juga telah menelan korban jiwa anak-anak yang tenggelam, mencemari air tanah, dan mengancam kawasan sekitar IKN.
Argumen pemerintah selalu kembali pada pertumbuhan ekonomi. Namun, ironisnya, sektor yang dikejar ini justru sedang goyah. Dilansir dari Katadata, Harga Batu bara Acuan (HBA) periode II September 2025 turun 1,75 persen menjadi US$ 103,49 per ton. Tak hanya itu, Investor Daily bahkan mencatat harga batu bara Newcastle per 8 Oktober 2025 turun US$ 0,65 menjadi US$ 90,35 per ton akibat kelebihan pasokan global dan terancam akan terus merosot.
Artinya, pemerintah mendorong ekspansi tambang di saat harga komoditas utama justru melemah. Keuntungan jangka pendek yang dikejar bisa jadi tidak sebanding dengan kerugian ekologis dan sosial yang ditanggung oleh masyarakat.
Tambang selalu identik dengan deforestasi. Setiap izin baru berarti pembukaan hutan, hilangnya habitat satwa, meningkatnya risiko banjir dan longsor serta masyarakat adat yang kehilangan hak ulayatnya. Jika kita menengok dokumen resmi negara, seperti Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang diterbitkan oleh Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah sendiri mengakui bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius berupa kehilangan keanekaragaman hayati akibat perubahan tata guna lahan, eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan deforestasi. IBSAP menegaskan bahwa keanekaragaman hayati adalah modal dasar pembangunan berkelanjutan dan menjadi penopang sistem kehidupan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, hingga mitigasi perubahan iklim.
Nahasnya, di saat negara menegaskan komitmen global untuk menjaga ekosistem melalui IBSAP, di saat itu pula hadir PP 39/2025 yang justru membuka ruang lebih luas bagi badan usaha selain korporasi untuk masuk ke sektor tambang. Padahal, IBSAP secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan ekosistem, restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi sebagai strategi utama untuk mencegah hilangnya spesies dan menjaga keseimbangan ekologi.
Dengan status ribuan lubang tambang di Kaltim yang belum direklamasi, puluhan ribu hektare lahan tambang tanpa Jamrek, serta harga batu bara yang terus merosot maka kebijakan memperluas izin tambang ke koperasi dan UMKM justru bertolak belakang dengan arah kebijakan ekologis nasional. Alih-alih memperkuat integritas ekosistem sebagaimana diamanatkan IBSAP, kebijakan ini berpotensi mempercepat deforestasi, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Jika koperasi dan UMKM yang minim pengalaman teknis diberi izin, potensi kerusakan akan semakin besar. Hutan yang tersisa bisa habis bukan karena korporasi besar saja, tetapi juga oleh ekonomi kerakyatan yang salah arah.
Pada akhirnya, kebijakan ini akan terus menimbulkan pertanyaan yang sama seperti di awal, jika regulasi ini benar-benar dihadirkan atas nama rakyat, rakyat yang mana yang dimaksud? Apakah rakyat yang menikmati dividen koperasi dan UMKM, atau rakyat yang harus menanggung banjir, longsor, dan udara kotor akibat tambang?
Sebab jika semua badan usaha bisa menambang, maka yang tersisa untuk generasi mendatang hanyalah lubang-lubang menganga, hutan yang hilang, dan bencana yang terus berulang.
Opini ini ditulis oleh Nabilah Nur Nujud, mahasiswa FH Unmul 2024