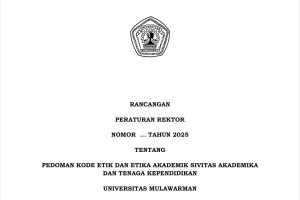Hentikan Rape Culture, Selamatkan Korban Pelecehan
Perlakuan wajar terhadap kasus pelecehan seksual di masyarakat harus dihentikan.
- 20 Jun 2021
- Komentar
- 2835 Kali

Sumber Gambar: Istimewa
SKETSA - Tak lagi asing di telinga, lonjakan kasus pelecehan seksual kian terdengar. Beberapa di antaranya sempat menyita perhatian publik, hingga perbincangan mengenai pelecehan seksual kembali menjadi topik yang hangat bahkan trending di media sosial.
Salah satu hal yang paling memprihatinkan adalah hadirnya narasi-narasi yang justru menyalahkan dan menyudutkan korban dengan beragam stigma dan victim blaming. Perempuan sebagai korban kerap mendapat komentar miring terhadap pakaian, pergaulan sampai tuduhan tidak bisa menjaga diri. Hal tersebut menciptakan "pemakluman" terhadap pelecehan seksual, juga menimbulkan penilaian bahwa masyarakat sendirilah yang menjadi faktor melanggengnya kasus pelecehan seksual.
Dalam perspektif budaya, pemakluman terhadap kasus pelecehan seksual tersebut merujuk pada istilah rape culture. Rape culture sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul dari Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an yang merespons adanya sebuah tindakan kewajaran terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di mata masyarakat.
Lantas, apa yang terjadi? Ketika laki-laki melakukan pelecehan terhadap perempuan, masyarakat menganggap hal ini biasa. Laki-laki sebagai pelaku, didukung dengan ideologi patriarki yang mengakar kuat di masyarakat. Sementara, perempuan yang menjadi korban kerap disalahkan dan masyarakat menganggap bahwa 'kodrat laki-laki’ memang seperti itu.
Indrawan Dwisetya Suhendi, dosen Gender dan Feminisme Fakultas Ilmu Budaya (FIB), mengungkap besarnya pengaruh ideologi patriarki terhadap rape culture. Sebuah penelitian tahun 2014 mengatakan, budaya patriarki di negara berkembang seperti Indonesia sangat mengakar kuat. Ideologi patriarki sebagai sebuah ideologi yang menganak emaskan laki-laki, menjadikan perempuan sebagai second sex atau setengah manusia. Hal tersebut didasarkan pada anggapan terdahulu bahwa perempuan dalam sejarah dipandang sebagai setengah manusia.
“Jadi, perlakuan laki-laki terhadap perempuan sering kali dinormalkan oleh ideologi patriarki yang sangat mengakar dan melembaga. Kalau ada perempuan diperkosa, pasti yang disalahkan adalah si perempuan itu. Itu sebagai bagian dari rape culture, menyalahkan korban," jelasnya kepada Sketsa melalui telepon pada Jumat (18/6) lalu.
Selain itu, Indrawan mengaku bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan victim blaming berakar dari kekuatan ideologi patriarki di masyarakat. Di mana perempuan sering kali menjadi korban sekaligus tertuduh dan disalahkan atas perbuatan yang menimpa dirinya. Ia kemudian menyinggung dan merasa aneh terhadap kasus pelecehan yang terjadi di musala yang belakangan sempat viral di media sosial.
“Nah komen-komen yang muncul, bisa kita temukan lebih banyak menyorot kenapa perempuan beribadah di luar rumah. Ini kan aneh. Masyarakat kita justru menyalahkan si perempuan karena dia salat di luar rumah, sementara perbuatan si laki-laki yang biadab itu justru sering kali bias.”
Baginya, hal tersebut merupakan satu indikasi bahwa rape culture sangat bias gender. Karena selalu menjadikan kelompok perempuan sebagai korban dan tertuduh, sementara kelompok laki-laki selalu mendapat privilese.
Meski kelompok perempuan mendominasi sebagai korban, hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya pelecehan terhadap kelompok laki-laki. Menurut Indrawan, siapa pun pelaku entah perempuan ataupun laki-laki patut disalahkan atas perbuatannya. Di sisi lain, dia juga mengungkap adanya konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya untuk mengatribusi jenis kelamin. Seperti keharusan bersikap sesuai jenis kelamin. Jika terlahir sebagai perempuan, maka harus seperti ini dan itu yang kemudian berlaku pula pada laki-laki.
Konstruksi sosial yang mengatribusi jenis kelamin tersebut pun berlaku pada pelecehan seksual. Dalam konteks perempuan sebagai pelaku pelecehan seksual, sering kali juga mengalami berbagai stigma di masyarakat. Seperti ungkapan ‘perempuan kok seperti itu?’ dan sebagainya.
“Itu juga sebenarnya bias gender, karena masyarakat menganggap perempuan sebagai sosok yang lemah sementara laki-laki sosok yang kuat. Maka akan diwajarkan oleh masyarakat apabila laki-laki memperkosa perempuan.”
“Tapi apabila seorang perempuan melecehkan laki-laki, maka si perempuan itu juga akan mengalami stigma. Misalkan stigmanya adalah 'perempuan kok seperti itu?', 'perempuan kok binal?' Intinya ada stigma yang menyalahkan kekuasaan si perempuan saat dia memperkosa laki-laki. Walaupun memang dalam konteks itu, jelas si perempuan salah.Tidak ada yang betul kalau seseorang melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual apa pun jenis kelaminnya," lanjutnya.
Selain terhadap perempuan, laki-laki sebagai korban juga mendapat komentar miring. Seperti anggapan bahwa laki-laki tersebut lemah, di mana dalam konstruksi sosial laki-laki diidealkan sebagai sosok yang kuat dan sudah seharusnya melakukan perlawanan. Padahal, pelecehan seksual dapat terjadi di mana-mana, dan tidak memandang jenis kelamin juga gender.
Beberapa korban yang sempat melakukan speak up terhadap pelecehan yang menimpa dirinya juga patut diapresiasi. Menurut Indrawan, speak up merupakan langkah paling penting dan paling esensial untuk mencegah maraknya kasus pelecehan.
“Karena dengan bicara, kamu bisa membuka mata dunia bahwa terjadi sesuatu hal yang mengerikan terhadap saya dan terjadi lingkungan sekitar. Nah dengan kamu speak up, dengan korban speak up maka masyarakat sekitar menjadi aware bahwa di lingkungannya ada pelaku pelecehan seksual. Maka akan muncul mekanisme-mekanisme hukum atau mekanisme-mekanisme sosial lainnya untuk mengontrol supaya peristiwa itu tidak terjadi lagi.”
Bagi Indrawan, ketidakmampuan korban untuk speak up menjadi salah satu penyebab angka kasus terus menerus meningkat. Ini berakar dari rape culture yang memposisikan korban sebagai pihak yang dituding dan acapkali mendapat komentar miring tadi.
Pendidikan seks juga menjadi langkah selanjutnya yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, peran keluarga terutama orang tua menjadi sangat penting dalam melakukan edukasi dan pembelajaran seks terhadap anak. Seperti makan, minum dan tidur, seks juga merupakan bagian yang melekat pada diri seseorang apa pun gendernya. Bukan sebagai hal yang tabu karena menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari. Nantinya, pendidikan seks justru akan membuka wawasan anak-anak dan remaja sehingga mereka akan berani melapor ketika telah menimpa mereka.
Sebagai penutup, ia mengajak mahasiswa untuk melawan budaya rape culture dari sistem ideologi patriarki yang sangat melembaga dan mengakar kuat.
“Jadi buat adik-adik mahasiswa, misalkan merasa mengalami pelecehan seksual entah itu di lingkungan kampus, lingkungan sekitar kampus maupun di lingkungan lain. Speak up, speak up kepada orang yang kamu percaya. Speak up kepada teman, sahabat, keluarga, orang yang berwajib supaya mereka bisa mengambil tindakan terhadap apa yang kamu alami. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan tubuhmu, jangan pernah takut memperjuangkan kemanusiaanmu yang sudah dirampas oleh si pelaku pelecehan tersebut. Jangan pernah takut speak up," pungkasnya. (zar/hdt/khn/rst)