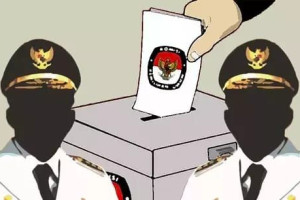“Air, tanah dan udara adalah milik negara dan dimanfaatkan seluas luasnya oleh negara bagi kepentingan rakyat”, demikian bunyi pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Nyatanya bukan isu tentang kiamat saja yang hangat di tahun 2012. Pasal yang saya sebutkan di atas menjadi sebuah perbincangan krusial setelah film dokumenter terobosan Ucu Agustin, Di Balik Frekuensi, disantap sebagian khalayak. Frekuensi, yang menjadi sebuah nyawa bagi keberlangsungan hidup sebuah stasiun televisi tidak lagi sepenuhnya milik publik.
Sejak bergulirnya era reformasi, kebebasan pers lepas dari belenggu. Media berlomba-lomba membangun sebuah kerajaan dengan aneka format. Mengapa saya katakan frekuensi bukan lagi milik publik? Sekarang ini, kalau saya bertanya adakah yang tidak tahu lagu Mars Perindo? Kecil kemungkinan mulut kita tidak mendendangkannya secara spontan, saking seringnya lagu tersebut diputar di televisi oleh Ketua Umum Partai Perindo sekaligus pemilik media raksasa MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.
Itu hanya satu contoh tayangan yang terafiliasi dengan kepentingan partai politik. Dalam film Di Balik Frekuensi, mengisahkan dua media besar yakni TVOne yang dikuasai oleh Abu Rizal Bakrie yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, serta Metro TV yang dimilki Surya Paloh sekaligus pendiri Ketua Umum Partai NasDem.
Kedua pengusaha tersebut sempat tersandung kasus yang hingga kini kejelasannya masih abu-abu. Membawa peran serta media yang mereka naungi sekaligus memberi tanya: Fungsi media sebagai kanal mengedukasi dan memberi kecerahan bagi publik sudah berubah haluankah?
Di Balik Frekuensi, mengisahkan Luviana, jurnalis Metro TV yang sudah bekerja selama sepuluh tahun sebagai Asisten Produser. Semula ia hendak dimutasi dari newsroom ke HRD, namun ia menolak. Kasus ini berbuntut panjang setelah Luvi mengkritisi manajemen MetroTV yang menolak berdirinya Serikat Kerja bagi pegawai Metro. Ia juga mempertanyakan deskjob yang seringkali Luvi berperan sebagai produser padahal ia wakil, dan juga gaji yang ia terima gaji asisten produser (disebutkan gajinya sebesar 1,8 juta). Luvi tiba-tiba saja di non-jobkan dan di PHK secara sepihak.
Bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Luvi melawan ketidakadilan. Aksi tersebut membawanya beraspirasi (bahkan, menangis) langsung di depan Surya Paloh yang berjanji Luviana secepatnya bisa kembali bekerja di Metro.
Namun bukannya hitam di atas putih kelanjutan kerja yang ia dapatkan, ia menerima surat berisi pemutusan hubungan kerja karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik stasiun Metro TV melalui aksinya bersama AJI.
Lain cerita di Sidoarjo, korban lumpur lapindo Hari Suwandi, melakukan aksi berjalan kaki dari Porong menuju Jakarta. Meminta pertanggungjawaban Abu Rizal Bakrie selaku orang yang ada dibalik merebaknya kasus Lumpur Lapindo, terkait pembayaran ganti rugi yang belum lunas.
Sepanjang perjalanan, Suwandi kerap merutuki dan antipati pada kehadiran media TVOne.
Lucunya, berita ini ditayangkan TVOne sebagai kebohongan belaka. Bahwa Suwandi berada dalam kendali pihak lain dalam melakukan aksinya. Bahkan berita tersebut dilengkapi wawancara dengan relawan lumpur lapindo yang menguak fakta Suwandi adalah orang Kediri, dan mengatakan tidak ada warga yang beraksi di luar daerah Sidoarjo.
Aksi yang semula dramatis dan heroik dengan melumuri tubuh dengan lumpur, Suwandi secara independen berjalan selama 29 hari memperjuangkan nasib korban lumpur lapindo tiba-tiba berakhir antiklimaks.
Suwandi muncul di TV One membawa istri dan cucu seraya menangis. Mengaku ditunggangi oleh pihak lain dan meminta maaf kepada Abu Rizal Bakri. Spontan saya tertegun melihat adegan ini. Ada apa dibalik perubahan sikap yang teramat drastis ini?
Kisah Suwandi ditutup dengan kalimat “Suwandi tidak kembali ke Sidoarjo dan hingga kini tidak diketahui dimana keberadaannya”.
Begitu juga Luviana, tak jelas bagaimana kabarnya saat ini.
Media yang seharusnya membantu tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa justru dijadikan alat mengkonfrontir pihak lawan dan membekaskan kebingungan pada masyarakat awam.
Hal ini menjadikan masyarakat sebagai pihak yang sangat dirugikan. Pun demikian dengan jurnalis. Sebagai buruh yang bekerja independen, kebebasan berserikat dan kewajibannya memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada publik diberangus.
Saya sedih sekali saat film dokumenter ini sampai pada tayangan Luviana melakukan demonstrasi di depan kantor Metro namun tidak seorang pun rekannya sesama jurnalis datang membantu.
Bahkan memberi komentar mengenai aksi ini saja tidak seorang pun kuasa. Bisa kita bayangkan betapa digdayanya orang yang membungkam hati nurani mereka bicara. Semata-mata demi dapur tetap mengepulkan asap, orang-orang dengan mudahnya kehilangan idealisme.
Konglomerasi media sudah sampai pada tahapan yang parah. Menyoroti hubungan antara media-pemerintah-jurnalis-dan publik bagaikan lingkaran setan yang sulit putus, namun bukan tidak mungkin dapat berhenti menghamba pada pemilik media.
Saya merangkum ada beberapa langkah yang sekiranya menjadikan kita sadar, kalau bukan kita (publik maupun penguasa) yang memperbaiki ini, siapa lagi?
Satu: Pemerintah, Ayo Bersikap Tegas!
Wacana mengenai larangan pemilik media diharamkan tergabung dalam partai politik bukan tak mengudara. Namun kita tahu pasti bahwa media dan pemerintah sama-sama saling membutuhkan. Contohnya dalam pemberitaan kabinet yang dimenangkan presiden yang diusung salah satu partai politik. Sudah selayaknya pemerintah bersikap netral dan menjadi penyejuk. Sekaligus memberi langkah nyata penindaklanjutan penyalahgunaan media yang membodohi publik.
Dua: Menjadi Jurnalis yang Mencari Gaji atau Pendengar Isak Tangis di Sekitar?
Polemik kebebasan pers selalu menjadi isu yang menarik. Badai perjalanan seorang jurnalis demi bisa menyampaikan kebenaran seolah tak pernah mereda. Terciptanya UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik tak jua membuat kenyataan di lapangan lebih baik. Seorang jurnalis perlu mendengar suara hati mereka, akan menyuarakan kemerdekaan jurnalis seperti Luviana, atau memihak pemilik media dan mengkontaminasi diri dengan berita yang tidak benar adanya?
Tiga: Publik Harus Cerdas Menghindari hoax
Di era teknologi, dengan mudahnya kita mengakses informasi dari platform sebagai media pembelajaran. Namun kita juga harus berhati-hati, karena fungsi tersebut bisa jadi berbalik sebagai media pembobrokan.
Seringkali kita melihat berita hoax tersebar dengan judul yang provokatif. Sebagai masyarakat, kita harus pintar memilah dan menyaring informasi.
Empat: Mahasiswa sebagai Agent of Change Juga Harus Berperan
Ya, saya menambahkan mahasiswa sebagai salah satu solusi. Mengapa? Mahasiswa adalah salah satu aset masa depan yang diharapkan dapat memperbaiki taraf kehidupan bangsa. Bukan tidak mungkin kita menjadi salah satu penyumbang pengusaha wiraswasta dengan mendirikan sebuah media yang bersih dari politik. Indonesia masih memiliki sedikit SDM dalam wirausaha. Bermimpi besar tentu tidak salah apabila itu mampu mengubah Indonesia jadi lebih baik.
Pembahasan di atas harusnya menumbuhkan gerakan yang lebih dalam mengenai keadilan pers dan melibatkan seluruh unsur. Laksana peristiwa 1998, sejarah telah mencatat kisah dalam “Di Balik Frekuensi” dan semoga kejadian seperti demikian tidak terulang kembali.
Ditulis oleh Khairunnisa Rengganis, mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2016 FISIP, seusai mengikuti Journalistic Camp Sketsa 2017.