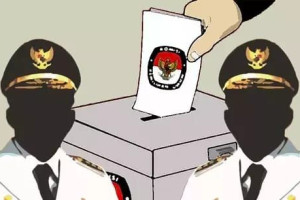Sumber Gambar: Website ANTARA News
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Samarinda turun ke jalan, meneriakkan protes terhadap keputusan DPR RI yang memprioritaskan pembahasan RUU Pilkada. Mereka menilai manuver tersebut sebagai upaya meloloskan pencalonan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, dalam pilkada serentak mendatang yang sebelumnya terganjal putusan Mahkamah Konstitusi.
Di tengah hiruk pikuk ajakan demonstrasi, sebuah unggahan story di Instagram menarik perhatian saya. Postingan tersebut menyebarkan gambar ajakan untuk aksi demonstrasi dengan tulisan "mahasiswa bergerak selamatkan demokrasi".
Saya langsung nyengir ketika membaca narasi itu. Kok tiba-tiba peduli demokrasi? “Itu lo, demokrasi kampusmu mati malah cuek,” pikir saya. Pikiran saya langsung merujuk pada proses Pemira (Pemilihan Raya) Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul di tahun ini. Di mana absennya kontestasi politik di dalam institusi pendidikan yang sering disebut sebagai “miniatur negara” tersebut.
Maksud saya, ya, meskipun hanya ada satu paslon setidaknya lawan kotak kosong gitu, lo. Walaupun di Sketsa mereka menyatakan telah mendapat sekitar seribu surat dukungan, tapi apakah itu cukup merepresentasikan mahasiswa Unmul yang jumlahnya kurang lebih 30 ribu orang? Atau minimal penyelenggara Pemira mengadakan uji publik untuk si duo tunggal ini.
Selain jadi ajang silaturahmi, ya bisa sekalian adu gagasan antara si peserta Pemira dan mahasiswa lain, yang secara langsung atau tidak, akan terseret almamaternya dalam gerakan-gerakan mereka ke depannya. Saya tidak bilang mereka bodoh atau tidak berkompeten. Justru karena saya yakin akan kemampuan mereka, maka dari itu saya agak menyayangkan mereka tidak diberi panggung untuk membuktikan itu.
Tapi, ya, mau bagaimana? Sudah terlanjur aklamasi. Sudah dilantik pula sepertinya. Kalau kata orang Samarinda, nasi dah jadi buras, wal ae.
Terus korelasi dengan judulnya apa? Begini, yang saya permasalahkan adalah mengapa kejadian penyimpangan demokrasi di tingkat nasional atau daerah langsung disorot dan dikritisi oleh para mahasiswa? Mengapa mereka tidak memberikan atensi dan daya pikir kritis yang sama ketika demokrasi di tempat mereka belajar kembali mati?
Apa mereka lupa bahwa mereka adalah mahasiswa PTN nomor 1 di Kalimantan? Apa mereka puas dengan kondisi demokrasi internal kampus mereka? Mengapa mereka mengibarkan slogan Vox Populi, Vox Dei di setiap sudut yang ada kecuali sudut kampus mereka sendiri?
Saya berani berkata, bahwa adalah suatu kemunafikan ketika ada seseorang yang mengaku pro-demokrasi tetapi tetap menghalalkan aklamasi dalam suatu proses pemilihan umum. Saya tidak tahu seberapa tebal bedak muka yang mereka gunakan ketika turun ke jalan, sehingga berani menyuarakan demokrasi sembari tak hirau dengan apa yang terjadi di kampus sendiri.
Apakah ini kemunafikan yang disengaja karena Presiden BEM KM yang terpilih membawa bendera-bendera koalisi yang sama dengan kepengurusan BEM KM yang sebelumnya? Saya jadi membayangkan skenario apa yang sekiranya terjadi jika ada dua paslon dan ternyata yang menang adalah kubu oposisi. Apapun reaksinya, yang jelas pasti tidak sekalem yang sekarang.
Kalau kampus adalah miniatur negara, berarti mahasiswanya adalah miniatur politisi. Itulah mantra yang saya ulang-ulang di dalam kepala agar menjadikan ironi yang saya saksikan sebagai sesuatu yang masuk akal. Kita perlu sadar bahwa politisi-politisi kurang ajar yang sekarang menjabat itu dulunya juga mahasiswa, kok. Mungkin sifatnya juga tidak ada bedanya dengan kita. Oportunis, munafik, pujungan, dan culas. Warna bendera lebih penting daripada kemampuan beretorika. Selama yang memegang jabatan masih kawan sendiri, bisalah ditoleransi.
Opini ini ditulis oleh Zain Aqil Hidayat, mahasiswa program studi Sastra Inggris, FIB Unmul 2018