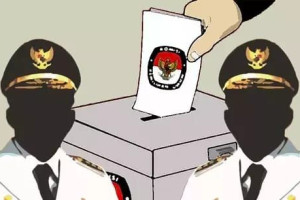Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
Saya sedang melewati Teras Samarinda saat melihat sekumpulan mahasiswa dengan beragam almamater berjalan beriringan. Di depan mereka, sebuah ‘mobil komando’ berjalan pelan. Persis seperti iring-iringan menuju lokasi demonstrasi. Di tangan mereka, tergenggam sebuah obor.
Rupa-rupanya, mereka sedang berjalan menuju Citra Niaga. Di sana, sedang dilakukan diskusi bertajuk ‘Kongkow Pemoeda’. Mengundang salah satu Calon Wali Kota dan Calon Wakil Gubernur. Mereka yang mengadakan acara itu menamakan diri mereka ‘Nyala Api Sumpah Pemuda’.
Di titik itu, saya merasa agak geli.
Namun kegelian saya tidak berhenti disitu. Tak jauh dari sana, lima menit perjalanan dengan sepeda motor, acara serupa digelar di Gedung Nasional yang baru saja direnovasi. Diadakan oleh sekumpulan orang yang menamakan diri mereka ‘Gema Pemuda Kaltim’.
Gimik mereka, saya akui cukup menarik. Sekumpulan ‘perwakilan’ sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim duduk melingkar, menyampaikan ‘aspirasi’ dan ‘keluhan’ dari daerah mereka masing-masing. Mereka semua memakai seragam putih, sebagian dengan ikat bendera Indonesia di kepalanya.
Tak hanya itu, dalam sebuah sesi, mereka bahkan menyalakan lilin bersama. Seseorang kemudian maju membawakan sebuah puisi. Lampu dimatikan membuat suasana semakin terkesan khidmat.
Sampai kemudian, beberapa jam acara berjalan, seorang mantan Wali Kota sebuah daerah di Kaltim hadir. Ia merupakan bagian dari tim pemenangan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Acara ‘Kongres Pemuda Kaltim’ hari itu berakhir dengan sebuah kesepakatan yang membuat saya bukan hanya geli, namun juga ingin muntah. Perwakilan dari daerah-daerah di Kaltim itu mendeklarasikan dukungan mereka ke salah satu pasangan calon di Pemilihan Gubernur Kaltim. Map berisi surat deklarasi diberikan kepada mantan Wali Kota yang tadi saya sebutkan.
***
Banyak pihak yang mengeluhkan hasil Pilpres 2024 kemarin. Saya merupakan salah satunya. Namun, jika beberapa menyalahkan beberapa hal seperti ‘bansos’ dan ‘putusan MK’, saya tak tahu harus menyalahkan siapa.
Hari itu, 14 Februari 2024 saya seharian di GOR 27 September, Unmul. Di gedung itu, digelar pemungutan suara khusus untuk mahasiswa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pendidikan di atas rata-rata. Meski tak semua, sebagian besar juga memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik.
Di sana, pasangan calon yang kita sebut-sebut sebagai pelanggar HAM dan anak haram konstitusi, menang telak. Mudah menuding ada kecurangan yang terjadi. Namun, saya tahu semua suara itu adalah suara riil.
Dalam prosesnya pun, saya sempat menanyai mereka satu persatu. Rasanya ngilu mendengar seorang mahasiswa mengatakan bahwa orang yang kita kenal sebagai pelanggar HAM itu, baginya adalah sosok yang dekat dengan rakyat. Referensinya adalah video-video singkat di media sosial.
Sehari atau dua hari setelah itu, saya menghapus media sosial saya dan vakum selama beberapa bulan. Saya begitu kecewa, dan sekali lagi, tak tahu harus menyalahkan siapa.
***
Novel “1984” karya George Orwell mungkin banyak dibahas lagi akhir-akhir ini. Setidaknya, oleh sebagian orang yang merasa bahwa rezim yang baru mungkin akan menghadirkan sifat otoritarianisme serupa. ‘Bung Besar’ ditakutkan akan melebarkan kekuasaannya hingga ke sudut-sudut kota.
Namun, menarik membaca pembahasan Neil Postman mengenai George Orwell dalam “Amusing Ourselves to Death”. Ia membandingkan George Orwell dengan Aldous Huxley. Jika George Orwell meramalkan dunia distopia dimana kebenaran dibungkam, Huxley meramalkan dunia distopia di mana kebenaran tak lagi berarti.
“Truth would be drowned in a sea of irrelevance”, begitu tulis Neil Postman. Dalam pencarian saya, kutipan sebenarnya dari Aldous Huxley dalam kumpulan esainya di Proper Studies adalah, “fact does not cease to exist because they are ignored”. Kebenaran tetap ada, akan tetapi keberadaannya diabaikan.
Secara sederhana, George Orwell meramalkan negara yang akan membungkam bahwa 2 + 2 = 4 dan menggantinya dengan propaganda bahwa 2 + 2 = 5. Sementara, Aldous Huxley percaya bahwa informasi 2 + 2 = 4 akan tetap ada, namun tenggelam dengan informasi-informasi lain yang menyebutkan bahwa 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 6, 2 + 2 =7.
Siapa atau apa yang kemudian bertanggung jawab? Media sosial? Jurnalis? Konsultan politik? Mahasiswa yang berpatron kepada senior-seniornya? Entahlah.
Yang jelas, bagi saya, demokrasi telah mati. Demokrasi telah sejak lama mati, dan kitalah yang membunuhnya.
Opini ini ditulis oleh Muhammad Al Fatih, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi FISIP Unmul 2022