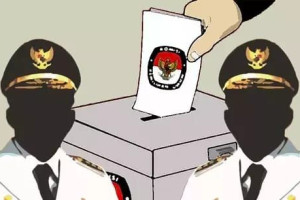Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
Beberapa waktu lalu, Balikpapan dihebohkan dengan demo sekumpulan sopir angkutan kota (angkot). Saat itu, Pemerintah Kota Balikpapan baru saja meluncurkan Balikpapan City Trans, transportasi publik dengan tampilan modern seperti Trans Jakarta. Sopir angkot yang selama ini beroperasi pun merasa periuk nasinya terancam.
Ada yang menyarankan, agar Balikpapan mengintegrasikan bus dengan angkot. Sementara bus bergerak di jalanan tengah kota, angkot dapat menjadi penghubung ke jalan-jalan yang lebih kecil. Istilah ilmiahnya dalam tata kota; feeder. Salah satu daerah yang telah menerapkan (atau bahkan mengenalkan) adalah DKI Jakarta, yang dikenal dengan Jaklingko.
Samarinda pun disebutkan akan menerapkan konsep serupa. Dalam salah satu kampanyenya, Wali Kota petahana Andi Harun, yang mencalonkan diri kembali dalam Pilwali tahun ini menyebutkan akan ada 4 Bus Rapid Transit (BRT) yang dilengkapi dengan 4 angkutan kota sebagai feeder-nya.
Tetapi, apakah ini hanya sebatas tentang bus dan angkot?
Dari Kota Modern ke Kota Partisipatif
Ada beberapa teori dalam komunikasi pembangunan sosial. Namun dalam artikel ini saya ingin menitikberatkan pada dua teori; modernitas dan partisipatif. Teori modernitas mendorong pada pertumbuhan yang masif, sementara teori partisipatif berfokus kepada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dua paradigma ini yang akan saya jadikan bahasan utama dalam tulisan ini.
Sedikit mundur ke belakang, saya ingin berbicara tentang Pemerintah DKI Jakarta di dua periode yang berbeda. Basuki Tjahaja Purnama, yang biasa kita kenal sebagai Ahok serta Anies Baswedan. Apa yang membedakan pemerintahan mereka berdua?
Pandangan mereka mengenai transportasi publik, misalnya. Pada era Ahok, ia menegaskan bahwa seluruh moda transportasi publik darat akan beralih ke Transjakarta. Supir angkot dan bus Kopaja, ia minta mendaftar menjadi supir Transjakarta. Jika tidak, mereka tidak boleh beroperasi sama sekali.
Pendekatan berbeda dilakukan Anies ketika ia menggantikan Ahok. Supir-supir angkot yang dianggap banyak orang tidak modern itu ia ajak berdiskusi. Tentu tidak serta merta berjalan lancar. Dalam sebuah kesempatan, ia bahkan menyebutkan diskusi berjalan alot hingga mesti dilakukan pertemuan berkali-kali.
Sampai akhirnya, dua tahun setelah ia terpilih, Jaklingko beroperasi. Supirnya digaji bulanan, metode pembayarannya (yang selama ini jadi keluhan pemakai angkot) pun diubah agar lebih jelas, dan tentu saja lebih murah.
Begitu pula ketika kita berbicara mengenai penggusuran. Kampung Aquarium, yang sebelumnya digusur pada era Ahok kemudian direvitalisasi di era Anies. Jika sebelumnya Ahok menerapkan ganti rugi bagi tanah yang digusur, Anies menerapkan ganti untung. Warga tak hanya diberi rumah susun, namun juga diajak berembuk langsung mengenai desain pembangunannya. Koperasi (yang kemudian bernama Koperasi Aquarium) kemudian hadir dan dikelola langsung oleh warga. Konsultan tata kota dilibatkan. Sebuah kolaborasi antara warga, pemerintah, dan pakar pun tercipta.
Ahok cenderung menggunakan paradigma modernitas dalam membangun Jakarta. Sementara, Anies menggunakan paradigma partisipatif. Saya tidak mengatakan satu lebih baik dibandingkan yang lain.
Dalam paradigma modernitas, pembangunan berjalan lebih masif. Paradigma partisipatif, minusnya membuat sebuah kebijakan menjadi terlalu bertele-tele. Lihat saja Kampung Bayam yang kini tak jelas nasibnya pasca Anies tak lagi memimpin.
Dalam mendorong pertumbuhan di Jakarta pun, Ahok tak pandang bulu. Pengelolaan anggaran yang tak jelas ia bereskan, hingga ia mengalami konflik dengan (almarhum) Haji Lulung. Pulau pribadi Surya Paloh, yang pengelolaannya ia anggap sembarangan pun ia segel.
Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara paradigma modernitas dan partisipatif. Dalam paradigma modernitas, pemerintah cenderung top-down, berlaku sebagai yang ‘paling tahu’. Sementara dalam paradigma partisipatif, pemerintah cenderung bottom-up dan berembuk berdiskusi dengan warga.
Kembali ke Andi Harun, ketika ia merencanakan integrasi bus dan angkot yang meniru konsep Jaklingko di Jakarta, ia serta merta melakukan komunikasi partisipatif. Apakah kebijakan itu telah ia bicarakan dengan pengusaha dan sopir angkot di Samarinda?
Andi Harun punya catatan yang kurang baik perihal keterlibatan masyarakat. Beberapa kebijakan ia terapkan tanpa berdiskusi dahulu dengan warga. Dalam penggusuran Pasar Pagi, ia bahkan berkata bahwa ‘hak asasi manusia dapat dikesampingkan untuk kepentingan publik’. Ketika mengucapkan itu, ia bersikap seolah yang paling tahu mengenai kepentingan publik.
Masih membekas di ingatan saya bagaimana guru-guru di Samarinda melakukan demonstrasi besar di Balai Kota. Padahal saat itu, masalahnya sederhana saja. Pemkot Samarinda ingin menyesuaikan pemberian insentif dengan mekanisme hukum terbaru. Sayang, karena kebijakan itu tak dibicarakan terlebih dahulu, membuat keributan hampir selama beberapa minggu.
Tulisan ini bukan untuk mendelegitimasi Andi Harun. Jujur saja, saya pun adalah salah satu pemilihnya nanti. Pembangunan ruang-ruang publik hingga drainase, perubahan di masa Andi Harun begitu terasa. Tak mungkin saya menafikannya, melihat Teras Samarinda dan Citra Niaga saja saya berdecak kagum. Namun, besar harapan saya, bahwa di kota yang ia gadang-gadang sebagai Kota Pusat Peradaban ini, ia akan mewujudkan Samarinda yang tak hanya maju kotanya, namun juga bahagia warganya.
Opini ini ditulis oleh Muhammad Al Fatih, mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP Unmul 2022