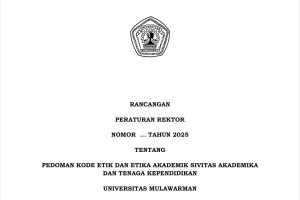Kacang Sembunyi Nenek
Cerpen soal kepergian.

Sumber Gambar: Istimewa
"Alma balik, ya, dah.." pamitku di teras rumah hendak pulang.
"Sebentar, ini buat jajan di bis," sebuah dialog yang aku hafal keluar dari mulut nenek, karena biasa terjadi.
Sangu dari nenek tak cuma uang, ia bisa menjejali tasku dengan kue kering yang saban tahun dia buat. Tangannya mulai keriput, entah memang menua atau karena terlalu lama menguleni bahan-bahan masakan. Satu yang selalu ada: cimi-cimi dan kacang sembunyi karamel.
Kau tahu tidak soal itu? Kurang beruntung rasanya jika stoples lebaranmu belum pernah diisi dengan dua kue kering legendaris itu. Buatan nenekku melampaui istimewanya kue nastar di pasaran. Tak perlu kehabisan waktu mengadon dan mengolesinya mentega telur agar kuning bersinar. Sebab cimi-cimi hanya perlu dipipihkan untuk selanjutnya kau bentuk pakai alat. Begitupun kacang sembunyi, kau hanya perlu mengiris serong adonan yang sudah tipis, agar bentuknya ciamik, dan menyembunyikan kacang tanah ke dalam lipatan adonan itu. Memandikannya minyak dan gula agar menjadi karamel.
Aku bukannya patissier—juru masak kue, tapi aku juru membantu nenek panas-panasan di depan oven tiga hari terakhir Ramadan. Aku gembira kalau menstruasi, karena artinya aku bebas buat minuman dingin di tengah krisis iklim menerpa seng rumah nenek yang dibeli murah, dan panas kompor menerpa kulitku. Menambah gelap aku yang sudah gelap.
Nikmatnya menjelma setan di tengah kerja rodi jelang lebaran, pikirku.
Usai lebaran, aku sering pulang ke Bontang, kota kecil yang setengah wilayahnya diapit dua perusahaan megah: Pupuk Kaltim dan LNG Badak. Apa yang aku lakukan? Biasanya hanya presensi menunjukkan batang hidung ke bapak. Hubungan kami tak langgeng layaknya bapak dan anak perempuan yang dimanja. Tak ideal sebagaimana media mainstream mengonstruksi hubungan keluarga inti: ibu, ayah, anak perempuan dan laki-laki. Bukan hanya perbedaan pandangan, keyakinanku dengannya menambah rentet jarak hubungan kami—lebih tepatnya karena orang lain sibuk mempertanyakan relasi beragama kami.
Tapi aku tak suka dikasihani orang-orang, sebab dianggap aku terlalu malang karena harus memilih agama. Aku menepisnya, karena rasa syukur dan pandanganku melebihi komentar-komentar tak masuk akal perkara kemanusiaan.
"Mengapa tidak ikut menjadi Nasrani kalau sudah tinggal dengan bapak?"
"Mengapa masih berjilbab, lingkunganmu Nasrani semua, lo"
"Ibumu sakit apa sebelum meninggal? Kasihan sekali karena sekarang kamu harus memilih menjadi Nasrani atau Muslim"
Di era Elon Musk mengejar rekor untuk meluncurkan 52 roket SpaceX, orang sekelilingku masih saja sibuk mengomentari keberagaman yang coba kutempuh. Sibuk sendiri mengganyang asumsi yang mereka buat.
Aku merayakan Idulfitri dan Natal. Datang ke Balikpapan berpuasa tiga puluh hari dan merayakan lebaran, beberapa bulan setelahnya ikut membantu dalam perayaan Natal. Apa yang salah dari itu?
Tapi kali ini, sebenarnya aku tak pulang hanya karena Natal, sebab tugas akhirku kadung bertandang di kota Bessai Berinta itu.
"Kapan lulusnya?," nenek selalu bertanya tiap aku ke Balikpapan, bergoler di sofa merah miliknya.
"Tunggu sehabis penelitian," aku menjawab sok-sokan meski dalam hati tidak tau kapan itu kulakukan.
Sebelum pindah ke Bontang untuk ikut bapak, aku dewasa bersama didikan ibu, lima belas tahun hidupku juga diisi dengan kebaikan hati nenek. Ibuku harus bekerja karena menjadi single parent. Semasa SD, aku tak kenal betul apa arti diantar, ditunggu, dan dijemput oleh orang tua. Tapi aku besar dengan cinta dan kasih dua orang nenek. Ibu dari bapak—seorang pensiunan guru dan Nasrani yang taat, berdoa tiga kali sehari di kamar. Serta ibu dari ibuku—seorang ibu rumah tangga, aktif berorganisasi, beken di kalangan ibu-ibu PKK.
---
Tiga bulan di Bontang, nenek--ibu dari ibuku, melakukan video call, tentu dibantu bibiku. Apalah nenekku si generasi baby boomers yang biasanya hanya memencet remot menonton Indosiar. Ia menanyakan kabar penelitianku. Nenek sakit saat itu, susah duduk dan susah makan. Biasanya, saat nenek sehat, dia mengadon kue, duduk di depan teve atau menyetel lantunan kasidah. Saban hari minum teh dan makan yang manis—yang selalu aku marahi karena dirinya punya riwayat diabetes.
Sebulan setelahnya, video call itu sudah tidak diisi dengan suara nenek. Karena dia kesulitan bicara, matanya susah terbuka. Aku bingung hendak basa-basi apa. Tapi yang jelas, aku yang saat itu memang ingin menangis, merapel ketidakjelasan emosi dan kesedihan di depan layar gawai. Air mata mengucur, segera aku bergegas untuk mencari bus, berangkat ke rumah nenek. Menempuh jarak lebih kurang 224 kilometer. Takut sekali jika malam ini Tuhan ambil nenek, sedang aku belum juga menyapa.
Aku jadi teringat satu kejadian saat 2015, pertama kalinya aku menjajaki Bontang.
"Halo, ini siapa?" suara akrab dari Balikpapan itu menyembur ke telinga, keluar dari speaker telepon rumah yang ku pegang. Aku yang saat itu tak punya ponsel pintar, memastikan.
"Ini Alma, ini betulkan nomor nenek?"
"Iya, kenapa? Kok enggak pernah telepon semenjak di sana?
Aku tarik napas, tak ingin nenek dengar aku terisak. Tapi kecengengan ini mendarah daging, dari mulai aku kecil, suka terjatuh saat main sepeda.
"Alma kangen," suaraku menggantung.
"Pengin pulang ke sana.."
Di seberang jalan sana, nenek hanya mendengarkan. Tau betul setiap menangis aku curi-curi waktu karena gengsi terlihat. Tapi kali itu aku tetap jadi anak kecil yang hanya pengin pulang. Kembali hidup biasa bersama nenek.
"Lebaran nanti ke sini aja," sahutan nenek menutup dialog saat itu.
-----
Pukul 2 siang.
Sesampainya di sana, nenek cuma terbaring. Rambut keritingnya yang dulu sering kuolok banyak yang memutih. Tubuhnya ringkih dan kurus, padahal dulu nenek selalu komentar tubuhku yang kecil seperti tak diberi makan. Namun, perkara membalikkan keadaan Tuhan paling bisa.
Dua hari usai aku sampai, nenek habis napas. Pertanda aku tidak bisa lagi memulai percakapan dengannya, dapat sangu uang, dan makan kue kering buatannya. Juga Ramadan ini akan sepi, lebih lagi lebaran. Tak ada deretan kue nenek berjejer di meja beralas taplak meja putih dan dengan emblem pink. Aku hapal menunya: cimi-cimi, kacang sembunyi, nastar, putri salju, madumongso, teh kotak, dan minuman cincau. Syukur jika ada opor ayam dan bolu pisang.
Usai ikut memandikan nenek, aku tak tau perpisahan bisa jadi sebegini lekatnya. Nenekku adalah hoarder—penimbun barang yang kunilai tak cukup bernilai. Aku, cucunya, adalah seorang yang suka semuanya tertata rapi, tanpa kehebohan pernak-pernik. Aku mudah membuang barang, bahkan yang sentimentil sekalipun. Nenek kerap salut dengan skill diam-diamku ini. Bengis membuang barang tanpa ragu sesekali. Hal yang sulit dilakukan oleh nenek berusia hampir tujuh puluh tahun. Kadang ia marah sebab barang ‘bernilainya’ ikut tergerus ke plastik kuning besar yang biasa kujadikan tempat sampah.
Kali ini, sulit. Membersihkan barang-barang nenek artinya membersihkan segala sudut soal nenek. Baru kali ini membuang barang jadi dilema bagiku. Kepergian nenek sebenarnya bukan hanya ketidakmampuan manusia untuk terhubung, tapi juga ketidakmampuan manusia menghitung berapa ingatan terlintas tentang orang yang baru saja pergi. Aku mengalaminya. Aku sadar bahwa aku mengalaminya.
Mengenang nenek bagiku sama dengan mengenang berapa kali aku teringat baju daster yang dia jahit sendiri pakai kain pembagian parpol, mengenang rambut keriwilnya, mengenang manisnya kacang sembunyi karamel buatan nenek. Terlebih mengingat kapan sisa waktuku untuk sampai di tahap yang nenek telah lewati.
Sebentar, bukankah kematian juga pencapaian terbesarnya manusia?
Cerita pendek ditulis oleh Restu Almalita, mahasiswi Ilmu Komunikasi, FISIP 2018.